Komunikasi politik juga ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, karena komunikasi selalu ditemui di belahan dunia manapun. Untuk lebih memahami lagi apa itu komunikasi politik, ada baiknya hal ini dijabarkan dalam beberapa contoh peristiwa komunikasi politik di Indonesia.
Tulisan dapat dilihat juga di http://catatankomunikasi.blogspot.com/
Pemilihan Umum
Pemilu (Pemilihan Umum) Presiden sudah tentu merupakan salah satu contoh komunikasi politik di Indonesia. Mengapa? Karena salah satu definisi politik adalah seni memperebutkan sesuatu, – dalam hal ini jabatan sebagai presiden.
Strategi dalam memperebutkan ‘bangku presiden’ ini salah satunya terdapat dalam pencitraan para calon presiden yang mengikuti pemilu.Pencitraan politik sebenarnya sudah merebak mulai Pemilu 1999 yang makin lama semakin berkembang hingga kini.
Masih ingat euforia Pemilu tahun 2009 lalu? Pencitraan Sutrisno Bachir, dari partai Partai Amanat Nasional (PAN), yang memanfaatkan momentum 100 tahun Kebangkitan Nasional dapat kita lihat dari iklan berslogan “Hidup adalah Perbuatan”. Wiranto, dari partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), secara dramatis ikut makan nasi aking bersama warga miskin dan mengiklankan tiga seri iklan bertema kemiskinan. Megawati Soekarno Putri, dari partai PDIP Perjuangan, yang dulu jarang berkomentar bahkan mengkritik pemerintah dalam ungkapan-ungkapannya, hingga mengukuhkan citranya sebagai figur yang peduli dengan wong cilik. Jusuf Kalla, dari partai Golongan Karya (Golkar), hadir dengan slogan “Lebih Cepat Lebih Baik” dan “Beri Bukti, Bukan Janji” yang mengklaim keberhasilan pembangunan infrastruktur dan swasembada beras adalah hasil kontribusinya pada partai Golkar. Juga pencitraan Susilo Bambang Yudhoyono, dari partai Demokrat, yang mencitrakan hasil-hasil positif dari kinerjanya sebagai presiden di tahun sebelumnya, seperti penurunan harga Bahan Bakar Minyak, beras untuk rakyat miskin, peningkatan angka pendidikan, dan lain-lain.
Dalam bukunya, Komunikasi Politik (1993), Dan Nimmo menjelaskan bahwa setidaknya ada empat macam pencitraan politik, yaitu pure publicity(publisitas melalui aktivitas masyarakat dengan setting sosial apa adanya) yang dapat dilihat dalam pencitraan politik Sutrisno Bachir dengan slogan “Hidup adalah Perbuatan” dan memanfaatkan momentum 100 tahun Kebangkitan Nasional, free ride publicity(memanfaatkan akses untuk publisitas) yang banyak terlihat pada kampanye dalam mensponsori kegiatan sosial di masyarakat, tie-in publicity (memanfaatkan kegiatan luar biasa untuk publisitas), dan paid publicity (publisitas berbayar lewat pembelian rubrik di media massa) yang terpampang pada advertorial di berbagai media massa dan spanduk-spanduknya.
Akan tetapi, politik akan berjalan dengan baik apabila komunikasi verbal dan nonverbal terjalin dengan baik pula. Citra yang sebenarnya akan dinilai bukan hanya dari tahap ‘pendekatan’ tetapi juga tahap ‘pacaran’, yaitu ketika para calon presiden yang telah terpilih menjadi presiden itu membuktikan apa yang telah dijanjikan dan dicitrakan sebelumnya.
Kebijakan Pembangunan Gedung DPR
Pemilu memang merupakan aktivitas komunikasi politik yang mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tidak hanya itu, kasus-kasus kecil dalam negara ini juga tak luput dari peristiwa komunikasi politik. Beberapa bulan silam peristiwa pembangunan gedung DPR baru bernilai milyaran rupiah sempat menuai banyak komentar dari masyarakat, terlebih komentar-komentar berbau negatif. Kebanyakan masyarakat menilai pembangunan gedung DPR baru merupakan suatu keborosan, karena banyak hal-hal tidak penting, seperti kolam renang dan fasilitas mewah lainnya, yang akan diadakan untuk memfasilitasi para petinggi negara tesebut. Masyarakat jelas menuai berbagai protes, apalagi melihat kinerja DPR yang masih dipandang negatif oleh mayoritas masyarakat.
Namun, nyatanya, Pramono Anung, wakil ketua DPR RI, dalam kuliah umum di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran pada beberapa bulan lalu menyatakan bahwa hal tersebut tidak benar dan hanya terjadi kesalahan komunikasi oleh konsultan yang menjelaskan sehingga menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat.
Komunikasi politik di atas menjadi salah satu komunikasi politik yang kurang efektif sehingga menimbulkan kesalahpahaman informasi antara pemerintah dan masyarakat.
Statement Foke Soal Pemerkosaan yang Dipicu Cara Berpakaian Perempuan
Selain itu, komunikasi politik juga terjadi pada pernyataan Fauzi Bowo, Gubernur DKI Jakarta, saat menanggapi masalah tindak pemerkosaan yang kini marak terjadi di angkutan umum dipicu oleh cara berpakaian perempuan. Foke, begitu Fauzi Bowo kerap disapa, pun langsung meralat statement-nya itu. Foke, yang dikutip dari Kompas Online, 17 September 2011, berkata, “Saya minta maaf, bahwa pernyataan saya sebelumnya salah tafsir, Saya sama sekali tidak bermaksud melecehkan kaum perempuan. Saya justru mengutuk aksi pemerkosaan tersebut, pelaku harus dihukum seberat-beratnya.”
Permintaan maafnya itu ia sampaikan karena pernyataan sebelumnya tentang rok mini menuai demo dari sekitar 50 perempuan yang menggelar aksinya di Bundaran HI, Jakarta, dengan memakai rok mini. Mereka menyatakan kekecewaannya terhadap ucapan Foke. Untungnya, Foke cepat menyatakan permohonan maaf.
Peristiwa tersebut termasuk dalam komunikasi politik, karena menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, politik juga adalah cara bertindak dalam menghadapi atau menangani suatu masalah. Hal ini menunjukan adanya komunikasi dalam dunia politik dalam menghadapi suatu masalah, yang mana komunikasi itu telah mewujudkan ruang dialog antara kalangan pemerintah dan kalangan masyarakat.
SBY Menanggapi Peristiwa SMS dan BBM Gelap
Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Indonesia, juga merupakan salah satu orang yang berperan dalam dunia komunikasi politik di Indonesia. Bagaimana tidak, ia adalah orang yang dalam mewujudkan politik itu sendiri. Politik di sini, menurut Plato, adalah cara mewujudkan dunia cita masyarakat menjadi dunia nyata, dan tentunya ia sangat berpengaruh, bukan?
Maka ketika ada persoalan SMS (Short Message Service) dan BBM (BlackBerry Messenger) gelap yang menyerangnya pada 28 Mei 2011 yang mengaku sebagai Nazarudin dengan bunyi, “Demi Allah, saya M Nazarudiin telah dijebak, dikorbankan, dan difitnah. Karakter, karier, masa depan saya dihancurkan. Dari Singapore saya akan membalas…”, masyarakat banyak yang membicarakan hal itu.
Daniel Sparingga, Staf Khusus Presiden bagian Politik, menegaskan,“SMS penuh tudingan tak berdasar ini sangat baik bagi sebuah dorongan yang lebih besar untuk tetap rendah hati dan berbuat lebih banyak lagi untuk kebajikan. Lebih penting dari semua itu, negeri ini memiliki banyak persoalan serius dan Pak SBY adalah pribadi serius yang diperlukan negeri ini. Tidak satupun SMS semacam itu akan mengalihkan perhatian SBY dari hal-hal serius. (dikutip dari detikcom, pada 29 Mei 2011)“
Komunikasi politik dalam peristiwa ini terlihat pada presiden SBY dan stafnya yang angkat bicara dan mengomunikasikan pada masyarakat tentang permasalahan presiden yang diangkat secara berlebihan di berbagai media massa saat itu.
Melihat dari berbagai peristiwa di atas, komunikasi politik di Indonesia memang belum sepenuhnya efektif.Kebebasan berpendapat yang seharusnya digunakan dengan baik tidak hanya oleh masyarakat tetapi juga oleh pemerintah, masih saja menuai konflik. Walaupun begitu, tanpa adanya komunikasi, politik di Indonesia akan pincang karena kehilangan salah satu sistemnya.
Pluralisme Pemilihan Gubernur DKI
Masih ingat bagaimana kecewanya warga Jakarta pada pemilukada tahun 2007 silam. Ya, ketika ibukota yang seharusnya menjadi barometer pluralisme dan demokrasi ini ternyata hanya memiliki dua pasang calon yang bertarung dalam pemilihan gubernur. Keduanya juga bukanlah orang yang punya record kepemimpinan yang mengesankan dan populer di mata masyarakat Jakarta. Alhasil seperti bisa ditebak, golput merajai banyak TPS pada waktu itu. Yang menang adalah oligarki partai yang selalu bergerombol untuk mencari celah transaksi politik. Outputnya, pasangan Fauzi Bowo dan Priyanto yang digadang-gadang koalisi mayoritas partai, harus pecah kongsi di tengah jalan karena kawin paksa politik.
Lima tahun berselang, kekhawatiran akan terulangnya kejadian serupa terus membayangi banyak warga Jakarta. Mengingat dari survei beberapa lembaga, popularitas dan elektabilitas incumbent Fauzi Bowo masih yang tertinggi. Harapan mulai tampak dari munculnya dua pasang calon independen yaitu Faisal Basri – Biem Benyamin dan Hendardji Soepandji – Riza Patria, yang keduanya kini sedang menghadapi verifikasi faktual akhir dari KPUD. Setelah pada pilkada 2007, calon independen masih harus menonton dari pinggir lapangan saat partai politik beraksi dan bertransaksi. Kini mereka bisa ikut meramaikan pertarungan di tengah lapangan, meskipun persyaratannya sangat tidak mudah.
Calon Independen menstimulus hadirnya calon terbaik
Buruknya komunikasi politik incumbent, serta hadirnya bursa calon independen ternyata menjadi salah satu pemicu partai politik untuk berlomba memunculkan calon terbaiknya. Kekhawatiran akan kembalinya dominasi Foke ternyata tidak terbukti. Proses penentuan bakal calon gubernur dan wakil gubernur oleh partai politik memang memunculkan tarik menarik hingga akhir batas tenggat waktu yang menarik untuk diikuti. Disinilah partai politik seakan terpacu untuk mengusung kader terbaiknya yang memiliki pengalaman memimpin daerah, populer, dinilai bersih dan berintegritas untuk bertarung.
Golkar yang sejak jauh hari mengatakan akan memilih cagubnya lewat survei, ternyata memilih sosok Alex Noerdin dan Nono Sampono yang tidak masuk dalam peredaran rekomendasi survei. Alex dipilih selain karena dinilai sukses sebagai bupati dua periode dan Gubernur Sumsel, dia juga mampu menggandeng dukungan dari dua partai yakni PPP dan PDS.
Meskipun masih bimbang di tingkat grass root karena nama Alex dan Nono sekonyong – konyong muncul, para elit kedua partai ini sepakat untuk mendukung penuh. Dari beberapa sumber dan media, diketahui bahwa mahar agar PPP mendukung Alex ternyata bernilai puluhan milyar. Sponsor kabarnya datang dari pengusaha dan penguasa tanah abang yang kini jadi menteri. Sang menteri diketahui publik memang sudah lama terlibat cekcok dengan Foke terkait penguasaan blok A tanah abang, yang amat menggiurkan dari segi bisnis itu.
Partai Demokrat yang mengalami kegalauan stadium lanjut terkait pilkada DKI, setelah sempat mengeluarkan statement akan menduetkan Foke dengan Adang Ruchiatna akhirnya menjatuhkan pilihan pada pasangan ”jeruk makan jeruk” Fauzi Bowo dan Nachrowi Ramli. Keduanya asal Betawi, separtai , serta menjadi Pembina berbagai orgnisasi keBetawian seperti Bamus Betawi, FBR, Forum Betawi Bersatu dll. Namun Golkar dan Demokrat tetap percaya bahwa komposisi sipil – militer tetap jadi pilihan, meskipun terbukti gagal jika berkaca pada duet Foke – Prijanto.
PKSpun yang selama ini menggadang nama Triwaksana, ketika mulai melihat pihak Demokrat menutup pintu koalisi dengan PKS, maka mereka mengeluarkan amunisi terakhirnya yaitu mencalonkan Hidayat Nurwahid, yang dipasangkan dengan Prof.Didik J Rachbini salah satu Ketua DPP PAN. Meskipun tidak didukung secara formal oleh PAN yang sudah menyatakan dukungan ke Foke, sosok Hidayat dinilai punya daya jual yang tinggi di Jakarta. Pada pemilu 2004, Hidayat Nurwahid adalah satu dari dua orang anggota parlemen terpilih yang berhasil mendapat suara mencapai bilangan pembagi pemilih.
Yang menarik adalah pilihan PDIP yang memutuskan untuk berkoalisi dengan Gerindra. Setelah hampir terjebak pada pragmatisme yang didorong Taufik Kiemas untuk berkoalisi mendukung Foke dengan potensi kemenangan dan uang yang besar , akhirnya pilihan jatuh pada Joko Widodo dan Ahok. Walikota Solo dan mantan Bupati Belitung Timur yang dikenal bersih dan sukses memimpin daerahnya. Jokowi misalnya, selain berhasil merelokasi PKL yang sudah puluhan tahun membuat semrawut dengan damai, juga sukses dengan program reformasi birokrasi pelayanan publiknya. Sementara Ahok seorang keturunan tionghoa disamping sukses memberikan jaminan asuransi kesehatan dan pendidikan untuk masyarakatnya di Belitung Timur, kehadirannya juga memperkuat identitas pluralitas Jakarta.
Adanya 6 pasangan calon pemimpin Jakarta yang sudah mendaftar, selain mampu memperkuat nilai demokrasi juga mampu mengakomodasi keberagaman warna etnis, tingkat ekonomi, pendidikan, pekerjaan dan warna politik warga Jakarta. Sejak era reformasi , tidak ada partai yang secara terus menerus bertahan menjadi penguasa di Jakarta. Di pemilu 1999 PDIP yang unggul, sementara PKS menjadi nomor satu di 2004, dan yang terakhir mendapat giliran menang di ibukota adalah Partai Demokrat. Tidak ada teori yang secara pasti bisa menjawab, selain fakta begitu dinamisnya politik Jakarta.
Menurut Survei terakhir Indobarometer, setelah melihat ada 6 calon yang akan bertarung, lebih dari 80 persen warga Jakarta menyatakan berniat memakai hak pilihnya di Pilkada bulan Juli nanti. Diharapkan di pilkada yang akan diprediksi dua putaran ini, warga DKI betul – betul menggunakan hak pilihnya secara bijak. Karena jika semakin banyak yang golput, maka calon incumbent yang kini berkuasa diprediksi akan makin mudah melenggang.
Wimar Witoelar pernah mengatakan, jika anda bingung atau bahkan tidak tahu mau memilih calon yang mana dalam sebuah pemilu, maka lihatlah siapa saja orang yang mendukung atau berdiri bersama calon itu. Karena setiap calon yang baik, pasti akan didukung oleh orang – orang yang baik pula.
Di era Suharto, DPR sering dijuluki Tiga-D: Duduk, Dengar, Duit. Komunikasi yang berlaku di masa itu adalah komunikasi searah, yaitu komunikasi dari atas ke bawah (top-down). Presiden memberikan petunjuk dan pengarahan, langsung disetujui oleh DPR (yang selalu didominasi oleh Golkar) dan para menteri serta gubernur. Kemudian Gubernur memberi petunjuk dan pengarahan kepada DPRD tingkat I dan para Bupati, dan Bupati ke DPRD tingkat II dan para camat, dan begitu seterusnya sampai pada tingkat desa.
Untuk mengelola negara sebesar Indonesia, dengan jumlah penduduk yang meningkat terus dari hampir 200 juta, sampai sekarang sudah mencapai 210 juta, dan heterogenitas penduduk yang sangat luar biasa, sistem komunikasi politik searah ini sudah terbukti sangat efektif selama 32 tahun. Tetapi sistem komunikasi ini terbukti tidak bisa bertahan selamanya. Bersamaan dengan Krisis Moneter yang berkembang juga menjadi Krisis Politik, rezim Suharto pun tumbang, dan pola komunikasi langsung berubah arah: dari bawah ke atas (bottom-up).
Namun pola komunikasi bawah-atas ini, langsung terbukti sama tidak efektifnya. Bahkan lebih tidak efektif, karena jika semasa Suharto yang terasa adalah keluhan pihak-pihak yang frustrasi karena aspirasinya tidak tersalur (misalnya: kelompok PDI Mega, Petisi 50, mahasiswa dsb.), pada era pasca-Suharto, yang terjadi adalah anarkhi yang tidak habis-habisnya, sehingga dalam tempo singkat presiden RI berganti 4 kali. Masalahnya, dalam pola atas-bawah, maupun bawah-atas, sama-sama tidak terjadi dialog (komunikasi dua arah), yang terjadi hanya monolog (komunikasi searah).
Dari Monolog ke Dialog
Semangat dialog nampak sangat mencuat sejak reformasi. Salah satu jargon yang sangat sering diucapkan dalam menyikapi berbagai masalah adalah “duduk bersama”. Seakan-akan semua masalah, dari kasus tawuran antar agama di Ambon dan Maluku Utara, konflik antar etnik di Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan, sampai kasus DOM Aceh, Tanjung Priok dan Timor Timur, dapat diselesaikan asalkan semua pihak mau duduk bersama.
Tetapi fakta juga membuktikan bahwa duduk bersama saja tidak bisa menyelesaikan apa-apa, jika semuanya hanya mau bicara dan mau didengarkan. Padahal menurut ilmu psikologi, salah satu syarat paling utama untuk sebuah dialog adalah kemampuan untuk mendengar aktif. Mendengar aktif, artinya bukan hanya bisa mendengar (to hear), tetapi juga mencari makna dari balik apa yang didengar (to listen), bahkan orang yang mendengar aktif, mampu menduga hal-hal yang tidak terungkapkan dalam kata-kata maupun perbuatan. Buat seorang yang mendengar aktif, “diam” adalah juga jawaban yang mengandung makna. Karena itu tidak sulit diterka, bahwa untuk mendengar aktif, yang merupakan prasyarat dari komunikasi yang dialogis, diperlukan kesiapan mental tertentu, yaitu kesiapan untuk berbagi (sharing), melepaskan sebagian pendapat, bahkan haknya untuk bisa menerima pendapat atau hak orang lain. Sikap yang ngotot, mau menang sendiri dan merasa benar sendiri, jelas bukan hal yang kondusif untuk mendengar aktif.
Kesiapan Mental
Dari pengalaman selama ini, kiranya sulit untuk dibantah bahwa kesiapan mental untuk berdialog antara lembaga eksekutif dan legislatif di negara kita masih jauh dari kenyataan. Istilah yang digunakan pun adalah “hearing” oleh DPR, bukan “listening”. Demikian pula DPR (DPRD) “memanggil” pemerintah (pemerintah daerah), persis seperti polisi memanggil tersangka. Sedangkan tata letak kursi-meja di ruang-ruang sidang komisi adalah sedemikian rupa sehingga ketua dan para wakil ketua, disertai para anggota duduk berhadapan dengan pemerintah (atau pihak lain yang didengar), persis sama dengan para hakim dan panitera, menghadapi terdakwa dan para saksi. Pendek kata, dalam tata-tertib hubungan pemerintah dan DPR, yang ada adalah hubungan a-simetris (DPR lebih tinggi dari pemerintah), bukan hubungan simetris (sejajar).
Hubungan a-simetris tidak selalu berarti jelek. Di lingkungan militer, dan perusahaan-perusahaan berteknologi tinggi yang menuntut zero error (misalnya: anjungan penambangan minyak, pesawat terbang atau kapal laut), dialog tetap bisa terjadi, walaupun pola komunikasinya a-simetris (tentunya melalui prosedur yang baku dan diberlakukan dengan sangat ketat). Syaratnya hanya satu: kedua pihak (atasan maupun bawahan) sama-sama menyadari peran dan posisinya masing-masing.
Masalahnya, anggota-anggota DPR kita, tidak siap untuk menerima peran dan posisi setara dalam komunikasi dialogis dengan pemerintah. Walaupun selalu kita dengar ucapan para politisi itu tentang kemitraan dan kesetaraan Pemerintah-DPR, yang ada justru pola komunikasi yang a-simetris seperti yang sudah diutarakan di atas.
Bahkan lebih memprihatinkan lagi, para anggota DPR ini tidak hanya menganggap pemerintah sebagai pihak yang statusnya lebih rendah, melainkan juga sesama anggota DPR sendiri. Itulah sebabnya sebulan pertama, DPR tidak bisa mulai bekerja, karena dua fraksi besar dalam DPR saling berselisih dan salah satu fraksi memilih untuk tidak masuk kantor saja selama sebulan. Lebih hebat lagi, pada saat membahas tentang kenaikan harga BBM, para anggota DPR bukannya saling adu argumentasi dengan pemerintah, tetapi malah saling berkelahi di antara mereka sendiri.
Tidak Siap Jadi Elit
Yang menarik, sebagian dari anggota DPR itu, beberapa saat sebelum dilantik adalah anggota masyarakat biasa. Ada yang artis, LSM, dosen, kiai dsb. Sebagai anggota masyarakat biasa, banyak (walaupun tidak semua) yang mempunyai reputasi yang baik: tidak punya track-record yang jelek, berintegritas, punya komitmen yang tinggi, pandangan-pandangannya mewakili pendapat rakyat dan seterusnya. Tetapi justru semuanya berubah setelah beliau-beliau menjadi anggota badan legislatif. Di daerah pun gejalanya sama.
Di lingkungan pemerintah (pusat maupun daerah), ternyata gejalanya tidak jauh berbeda. Kasus KPU misalnya, kalau pelanggaran pidananya benar terbukti, menunjukkan kepada kita betapa orang-orang berintegritas tinggi, bisa berubah sikap begitu masuk ke jajaran elite. Demikian pula halnya dengan para kepala daerah dan pejabat-pejabat daerah (tingkat propinsi maupun kabupaten) yang dikenal sebagai orang yang berintegritas tinggi, namun disuruh turun oleh rakyat begitu mereka menduduki jabatannya. Di tingkat partai politik, hampir tidak ada orang yang bisa terpilih menjadi ketua umum, tanpa menuai protes dari kelompok pesaingnya. Dan sikap yang diambil oleh yang menang maupun yang kalah adalah sikap konfrontatif (adu otot), karena memang rata-rata orang Indonesia masih lebih mengandalkan otot ketimbang hati sanubari.
Kesimpulannya, nampaknya watak bangsa Indonesia hanya baik jika mereka menjadi rakyat jelata, namun segera berubah ketika mereka masuk ke tingkat elit. Dengan perkataan lain, sebagian terbesar masayarakat Indonesia hanya siap jadi rakyat, tetapi tidak siap untuk menjadi elit. Begitu menjadi elit (apa pun, tidak hanya anggota DPR dan Pemerintah) maka akan terjadi perubahan mental yang signifikan. Karena itulah orang Indonesia lebih disiplin kalau dipimpin atau dimanajeri oleh seorang “bule”, ketimbang oleh pribumi sendiri.
Upaya
Menurut para pakar, ada dua macam jalan keluar dari komunikasi yang macet ini. Sebagian pakar (seperti John Naisbit, penulis buku “Milenium ke-Tiga”, dan Tu Weiming, Guru Besar Sejarah Agama-agama dari Universitas Harvard) berpendapat bahwa proses chaos ini akan berakhir sendiri, karena hanya merupakan bagian dari proses evolusi teknologi komunikasi dan informasi yang berskala jauh lebih besar, yang pada satu titik akan mencapai keseimbangan (equilibrium) sendiri secara alamiah (nilai baru, norma baru, tatanan masyarakat baru dsb. yang lebih adil, lebih manusiawi dsb.). Tetapi kapan saat itu akan tiba? Tidak ada yang bisa memastikan.
Pendapat kedua adalah dengan intervensi yang sistimatis dan terprogram. Paradigma inilah yang ditawarkan Suharto dulu, tatkala ia akan lengser. Dia menyatakan akan menata dulu pemerintahan selama 6 bulan ke depan, dan setelah itu ia tidak akan mencalonkan diri lagi menjadi presiden. Namun rupanya tawaran itu ditolak mentah-mentah oleh masyarakat yang sedang haus demokrasi. Pasalnya, memang intervensi atau social engineering menuntut pengorbanan, seperti: rakyat harus diatur dengan ketat, beberapa kebebasan ditarik dari masyarakat dsb. (seperti yang terjadi di Malaysia dan Singapura), padahal hal-hal yang harus dikorbankan itu, justru yang baru kita peroleh melalui reformasi dan pengorbanan jiwa. Maka terjadilah seperti yang kita alami sekarang.
Mana dari kedua strategi itu yang akan diikuti, kiranya akan sangat tergantung kepada kemampuan dan kemauan pemerintah, khususnya presiden dan wakilnya. Presiden dan wapres hasil Pemilu langsung sebenarnya mempunyai posisi yang sangat kuat dan tidak bisa begitu saja di dikte, apalagi di-impeach oleh DPR. Karena itu ia cukup punya legitimasi untuk menentukan pola permainan dan komunikasi politik yang akan berlaku. Kalau perlu dengan sedikit ketegasan. Gejolak pasti terjadi, tetapi tidak akan lama, karena kalau rakyat sudah melihat manfaatnya, maka protes akan berhenti dengan sendirinya (analoginya: Busway di DKI, awalnya sempat mengundang protes, tetapi sekarang hampir semua orang pernah menikmatinya, dan protes pun segera terhenti dengan sendirinya).
Namun kalau presiden masih tetap lebih suka mendengarkan dan mempertimbangkan suara-suara sumbang yang tidak habis-habisnya, termasuk dari golongan yang sudah jelas-jelas bersalah di mata hukum (seperti pedagang kaki lima, pengunjuk rasa yang membakar foto Presiden dsb.) demi demokrasi itu sendiri, maka memang kita tidak bisa mengharapkan banyak dari komunikasi-komunikasi antara DPR dan pemerintah di masa yang akan datang.
Tulisan dapat dilihat juga di http://catatankomunikasi.blogspot.com/
Pemilihan Umum
Pemilu (Pemilihan Umum) Presiden sudah tentu merupakan salah satu contoh komunikasi politik di Indonesia. Mengapa? Karena salah satu definisi politik adalah seni memperebutkan sesuatu, – dalam hal ini jabatan sebagai presiden.
Strategi dalam memperebutkan ‘bangku presiden’ ini salah satunya terdapat dalam pencitraan para calon presiden yang mengikuti pemilu.Pencitraan politik sebenarnya sudah merebak mulai Pemilu 1999 yang makin lama semakin berkembang hingga kini.
Masih ingat euforia Pemilu tahun 2009 lalu? Pencitraan Sutrisno Bachir, dari partai Partai Amanat Nasional (PAN), yang memanfaatkan momentum 100 tahun Kebangkitan Nasional dapat kita lihat dari iklan berslogan “Hidup adalah Perbuatan”. Wiranto, dari partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), secara dramatis ikut makan nasi aking bersama warga miskin dan mengiklankan tiga seri iklan bertema kemiskinan. Megawati Soekarno Putri, dari partai PDIP Perjuangan, yang dulu jarang berkomentar bahkan mengkritik pemerintah dalam ungkapan-ungkapannya, hingga mengukuhkan citranya sebagai figur yang peduli dengan wong cilik. Jusuf Kalla, dari partai Golongan Karya (Golkar), hadir dengan slogan “Lebih Cepat Lebih Baik” dan “Beri Bukti, Bukan Janji” yang mengklaim keberhasilan pembangunan infrastruktur dan swasembada beras adalah hasil kontribusinya pada partai Golkar. Juga pencitraan Susilo Bambang Yudhoyono, dari partai Demokrat, yang mencitrakan hasil-hasil positif dari kinerjanya sebagai presiden di tahun sebelumnya, seperti penurunan harga Bahan Bakar Minyak, beras untuk rakyat miskin, peningkatan angka pendidikan, dan lain-lain.
Dalam bukunya, Komunikasi Politik (1993), Dan Nimmo menjelaskan bahwa setidaknya ada empat macam pencitraan politik, yaitu pure publicity(publisitas melalui aktivitas masyarakat dengan setting sosial apa adanya) yang dapat dilihat dalam pencitraan politik Sutrisno Bachir dengan slogan “Hidup adalah Perbuatan” dan memanfaatkan momentum 100 tahun Kebangkitan Nasional, free ride publicity(memanfaatkan akses untuk publisitas) yang banyak terlihat pada kampanye dalam mensponsori kegiatan sosial di masyarakat, tie-in publicity (memanfaatkan kegiatan luar biasa untuk publisitas), dan paid publicity (publisitas berbayar lewat pembelian rubrik di media massa) yang terpampang pada advertorial di berbagai media massa dan spanduk-spanduknya.
Akan tetapi, politik akan berjalan dengan baik apabila komunikasi verbal dan nonverbal terjalin dengan baik pula. Citra yang sebenarnya akan dinilai bukan hanya dari tahap ‘pendekatan’ tetapi juga tahap ‘pacaran’, yaitu ketika para calon presiden yang telah terpilih menjadi presiden itu membuktikan apa yang telah dijanjikan dan dicitrakan sebelumnya.
Kebijakan Pembangunan Gedung DPR
Pemilu memang merupakan aktivitas komunikasi politik yang mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tidak hanya itu, kasus-kasus kecil dalam negara ini juga tak luput dari peristiwa komunikasi politik. Beberapa bulan silam peristiwa pembangunan gedung DPR baru bernilai milyaran rupiah sempat menuai banyak komentar dari masyarakat, terlebih komentar-komentar berbau negatif. Kebanyakan masyarakat menilai pembangunan gedung DPR baru merupakan suatu keborosan, karena banyak hal-hal tidak penting, seperti kolam renang dan fasilitas mewah lainnya, yang akan diadakan untuk memfasilitasi para petinggi negara tesebut. Masyarakat jelas menuai berbagai protes, apalagi melihat kinerja DPR yang masih dipandang negatif oleh mayoritas masyarakat.
Namun, nyatanya, Pramono Anung, wakil ketua DPR RI, dalam kuliah umum di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran pada beberapa bulan lalu menyatakan bahwa hal tersebut tidak benar dan hanya terjadi kesalahan komunikasi oleh konsultan yang menjelaskan sehingga menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat.
Komunikasi politik di atas menjadi salah satu komunikasi politik yang kurang efektif sehingga menimbulkan kesalahpahaman informasi antara pemerintah dan masyarakat.
Statement Foke Soal Pemerkosaan yang Dipicu Cara Berpakaian Perempuan
Selain itu, komunikasi politik juga terjadi pada pernyataan Fauzi Bowo, Gubernur DKI Jakarta, saat menanggapi masalah tindak pemerkosaan yang kini marak terjadi di angkutan umum dipicu oleh cara berpakaian perempuan. Foke, begitu Fauzi Bowo kerap disapa, pun langsung meralat statement-nya itu. Foke, yang dikutip dari Kompas Online, 17 September 2011, berkata, “Saya minta maaf, bahwa pernyataan saya sebelumnya salah tafsir, Saya sama sekali tidak bermaksud melecehkan kaum perempuan. Saya justru mengutuk aksi pemerkosaan tersebut, pelaku harus dihukum seberat-beratnya.”
Permintaan maafnya itu ia sampaikan karena pernyataan sebelumnya tentang rok mini menuai demo dari sekitar 50 perempuan yang menggelar aksinya di Bundaran HI, Jakarta, dengan memakai rok mini. Mereka menyatakan kekecewaannya terhadap ucapan Foke. Untungnya, Foke cepat menyatakan permohonan maaf.
Peristiwa tersebut termasuk dalam komunikasi politik, karena menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, politik juga adalah cara bertindak dalam menghadapi atau menangani suatu masalah. Hal ini menunjukan adanya komunikasi dalam dunia politik dalam menghadapi suatu masalah, yang mana komunikasi itu telah mewujudkan ruang dialog antara kalangan pemerintah dan kalangan masyarakat.
SBY Menanggapi Peristiwa SMS dan BBM Gelap
Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Indonesia, juga merupakan salah satu orang yang berperan dalam dunia komunikasi politik di Indonesia. Bagaimana tidak, ia adalah orang yang dalam mewujudkan politik itu sendiri. Politik di sini, menurut Plato, adalah cara mewujudkan dunia cita masyarakat menjadi dunia nyata, dan tentunya ia sangat berpengaruh, bukan?
Maka ketika ada persoalan SMS (Short Message Service) dan BBM (BlackBerry Messenger) gelap yang menyerangnya pada 28 Mei 2011 yang mengaku sebagai Nazarudin dengan bunyi, “Demi Allah, saya M Nazarudiin telah dijebak, dikorbankan, dan difitnah. Karakter, karier, masa depan saya dihancurkan. Dari Singapore saya akan membalas…”, masyarakat banyak yang membicarakan hal itu.
Daniel Sparingga, Staf Khusus Presiden bagian Politik, menegaskan,“SMS penuh tudingan tak berdasar ini sangat baik bagi sebuah dorongan yang lebih besar untuk tetap rendah hati dan berbuat lebih banyak lagi untuk kebajikan. Lebih penting dari semua itu, negeri ini memiliki banyak persoalan serius dan Pak SBY adalah pribadi serius yang diperlukan negeri ini. Tidak satupun SMS semacam itu akan mengalihkan perhatian SBY dari hal-hal serius. (dikutip dari detikcom, pada 29 Mei 2011)“
Komunikasi politik dalam peristiwa ini terlihat pada presiden SBY dan stafnya yang angkat bicara dan mengomunikasikan pada masyarakat tentang permasalahan presiden yang diangkat secara berlebihan di berbagai media massa saat itu.
Melihat dari berbagai peristiwa di atas, komunikasi politik di Indonesia memang belum sepenuhnya efektif.Kebebasan berpendapat yang seharusnya digunakan dengan baik tidak hanya oleh masyarakat tetapi juga oleh pemerintah, masih saja menuai konflik. Walaupun begitu, tanpa adanya komunikasi, politik di Indonesia akan pincang karena kehilangan salah satu sistemnya.
Pluralisme Pemilihan Gubernur DKI
Masih ingat bagaimana kecewanya warga Jakarta pada pemilukada tahun 2007 silam. Ya, ketika ibukota yang seharusnya menjadi barometer pluralisme dan demokrasi ini ternyata hanya memiliki dua pasang calon yang bertarung dalam pemilihan gubernur. Keduanya juga bukanlah orang yang punya record kepemimpinan yang mengesankan dan populer di mata masyarakat Jakarta. Alhasil seperti bisa ditebak, golput merajai banyak TPS pada waktu itu. Yang menang adalah oligarki partai yang selalu bergerombol untuk mencari celah transaksi politik. Outputnya, pasangan Fauzi Bowo dan Priyanto yang digadang-gadang koalisi mayoritas partai, harus pecah kongsi di tengah jalan karena kawin paksa politik.
Lima tahun berselang, kekhawatiran akan terulangnya kejadian serupa terus membayangi banyak warga Jakarta. Mengingat dari survei beberapa lembaga, popularitas dan elektabilitas incumbent Fauzi Bowo masih yang tertinggi. Harapan mulai tampak dari munculnya dua pasang calon independen yaitu Faisal Basri – Biem Benyamin dan Hendardji Soepandji – Riza Patria, yang keduanya kini sedang menghadapi verifikasi faktual akhir dari KPUD. Setelah pada pilkada 2007, calon independen masih harus menonton dari pinggir lapangan saat partai politik beraksi dan bertransaksi. Kini mereka bisa ikut meramaikan pertarungan di tengah lapangan, meskipun persyaratannya sangat tidak mudah.
Calon Independen menstimulus hadirnya calon terbaik
Buruknya komunikasi politik incumbent, serta hadirnya bursa calon independen ternyata menjadi salah satu pemicu partai politik untuk berlomba memunculkan calon terbaiknya. Kekhawatiran akan kembalinya dominasi Foke ternyata tidak terbukti. Proses penentuan bakal calon gubernur dan wakil gubernur oleh partai politik memang memunculkan tarik menarik hingga akhir batas tenggat waktu yang menarik untuk diikuti. Disinilah partai politik seakan terpacu untuk mengusung kader terbaiknya yang memiliki pengalaman memimpin daerah, populer, dinilai bersih dan berintegritas untuk bertarung.
Golkar yang sejak jauh hari mengatakan akan memilih cagubnya lewat survei, ternyata memilih sosok Alex Noerdin dan Nono Sampono yang tidak masuk dalam peredaran rekomendasi survei. Alex dipilih selain karena dinilai sukses sebagai bupati dua periode dan Gubernur Sumsel, dia juga mampu menggandeng dukungan dari dua partai yakni PPP dan PDS.
Meskipun masih bimbang di tingkat grass root karena nama Alex dan Nono sekonyong – konyong muncul, para elit kedua partai ini sepakat untuk mendukung penuh. Dari beberapa sumber dan media, diketahui bahwa mahar agar PPP mendukung Alex ternyata bernilai puluhan milyar. Sponsor kabarnya datang dari pengusaha dan penguasa tanah abang yang kini jadi menteri. Sang menteri diketahui publik memang sudah lama terlibat cekcok dengan Foke terkait penguasaan blok A tanah abang, yang amat menggiurkan dari segi bisnis itu.
Partai Demokrat yang mengalami kegalauan stadium lanjut terkait pilkada DKI, setelah sempat mengeluarkan statement akan menduetkan Foke dengan Adang Ruchiatna akhirnya menjatuhkan pilihan pada pasangan ”jeruk makan jeruk” Fauzi Bowo dan Nachrowi Ramli. Keduanya asal Betawi, separtai , serta menjadi Pembina berbagai orgnisasi keBetawian seperti Bamus Betawi, FBR, Forum Betawi Bersatu dll. Namun Golkar dan Demokrat tetap percaya bahwa komposisi sipil – militer tetap jadi pilihan, meskipun terbukti gagal jika berkaca pada duet Foke – Prijanto.
PKSpun yang selama ini menggadang nama Triwaksana, ketika mulai melihat pihak Demokrat menutup pintu koalisi dengan PKS, maka mereka mengeluarkan amunisi terakhirnya yaitu mencalonkan Hidayat Nurwahid, yang dipasangkan dengan Prof.Didik J Rachbini salah satu Ketua DPP PAN. Meskipun tidak didukung secara formal oleh PAN yang sudah menyatakan dukungan ke Foke, sosok Hidayat dinilai punya daya jual yang tinggi di Jakarta. Pada pemilu 2004, Hidayat Nurwahid adalah satu dari dua orang anggota parlemen terpilih yang berhasil mendapat suara mencapai bilangan pembagi pemilih.
Yang menarik adalah pilihan PDIP yang memutuskan untuk berkoalisi dengan Gerindra. Setelah hampir terjebak pada pragmatisme yang didorong Taufik Kiemas untuk berkoalisi mendukung Foke dengan potensi kemenangan dan uang yang besar , akhirnya pilihan jatuh pada Joko Widodo dan Ahok. Walikota Solo dan mantan Bupati Belitung Timur yang dikenal bersih dan sukses memimpin daerahnya. Jokowi misalnya, selain berhasil merelokasi PKL yang sudah puluhan tahun membuat semrawut dengan damai, juga sukses dengan program reformasi birokrasi pelayanan publiknya. Sementara Ahok seorang keturunan tionghoa disamping sukses memberikan jaminan asuransi kesehatan dan pendidikan untuk masyarakatnya di Belitung Timur, kehadirannya juga memperkuat identitas pluralitas Jakarta.
Adanya 6 pasangan calon pemimpin Jakarta yang sudah mendaftar, selain mampu memperkuat nilai demokrasi juga mampu mengakomodasi keberagaman warna etnis, tingkat ekonomi, pendidikan, pekerjaan dan warna politik warga Jakarta. Sejak era reformasi , tidak ada partai yang secara terus menerus bertahan menjadi penguasa di Jakarta. Di pemilu 1999 PDIP yang unggul, sementara PKS menjadi nomor satu di 2004, dan yang terakhir mendapat giliran menang di ibukota adalah Partai Demokrat. Tidak ada teori yang secara pasti bisa menjawab, selain fakta begitu dinamisnya politik Jakarta.
Menurut Survei terakhir Indobarometer, setelah melihat ada 6 calon yang akan bertarung, lebih dari 80 persen warga Jakarta menyatakan berniat memakai hak pilihnya di Pilkada bulan Juli nanti. Diharapkan di pilkada yang akan diprediksi dua putaran ini, warga DKI betul – betul menggunakan hak pilihnya secara bijak. Karena jika semakin banyak yang golput, maka calon incumbent yang kini berkuasa diprediksi akan makin mudah melenggang.
Wimar Witoelar pernah mengatakan, jika anda bingung atau bahkan tidak tahu mau memilih calon yang mana dalam sebuah pemilu, maka lihatlah siapa saja orang yang mendukung atau berdiri bersama calon itu. Karena setiap calon yang baik, pasti akan didukung oleh orang – orang yang baik pula.
Di era Suharto, DPR sering dijuluki Tiga-D: Duduk, Dengar, Duit. Komunikasi yang berlaku di masa itu adalah komunikasi searah, yaitu komunikasi dari atas ke bawah (top-down). Presiden memberikan petunjuk dan pengarahan, langsung disetujui oleh DPR (yang selalu didominasi oleh Golkar) dan para menteri serta gubernur. Kemudian Gubernur memberi petunjuk dan pengarahan kepada DPRD tingkat I dan para Bupati, dan Bupati ke DPRD tingkat II dan para camat, dan begitu seterusnya sampai pada tingkat desa.
Untuk mengelola negara sebesar Indonesia, dengan jumlah penduduk yang meningkat terus dari hampir 200 juta, sampai sekarang sudah mencapai 210 juta, dan heterogenitas penduduk yang sangat luar biasa, sistem komunikasi politik searah ini sudah terbukti sangat efektif selama 32 tahun. Tetapi sistem komunikasi ini terbukti tidak bisa bertahan selamanya. Bersamaan dengan Krisis Moneter yang berkembang juga menjadi Krisis Politik, rezim Suharto pun tumbang, dan pola komunikasi langsung berubah arah: dari bawah ke atas (bottom-up).
Namun pola komunikasi bawah-atas ini, langsung terbukti sama tidak efektifnya. Bahkan lebih tidak efektif, karena jika semasa Suharto yang terasa adalah keluhan pihak-pihak yang frustrasi karena aspirasinya tidak tersalur (misalnya: kelompok PDI Mega, Petisi 50, mahasiswa dsb.), pada era pasca-Suharto, yang terjadi adalah anarkhi yang tidak habis-habisnya, sehingga dalam tempo singkat presiden RI berganti 4 kali. Masalahnya, dalam pola atas-bawah, maupun bawah-atas, sama-sama tidak terjadi dialog (komunikasi dua arah), yang terjadi hanya monolog (komunikasi searah).
Dari Monolog ke Dialog
Semangat dialog nampak sangat mencuat sejak reformasi. Salah satu jargon yang sangat sering diucapkan dalam menyikapi berbagai masalah adalah “duduk bersama”. Seakan-akan semua masalah, dari kasus tawuran antar agama di Ambon dan Maluku Utara, konflik antar etnik di Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan, sampai kasus DOM Aceh, Tanjung Priok dan Timor Timur, dapat diselesaikan asalkan semua pihak mau duduk bersama.
Tetapi fakta juga membuktikan bahwa duduk bersama saja tidak bisa menyelesaikan apa-apa, jika semuanya hanya mau bicara dan mau didengarkan. Padahal menurut ilmu psikologi, salah satu syarat paling utama untuk sebuah dialog adalah kemampuan untuk mendengar aktif. Mendengar aktif, artinya bukan hanya bisa mendengar (to hear), tetapi juga mencari makna dari balik apa yang didengar (to listen), bahkan orang yang mendengar aktif, mampu menduga hal-hal yang tidak terungkapkan dalam kata-kata maupun perbuatan. Buat seorang yang mendengar aktif, “diam” adalah juga jawaban yang mengandung makna. Karena itu tidak sulit diterka, bahwa untuk mendengar aktif, yang merupakan prasyarat dari komunikasi yang dialogis, diperlukan kesiapan mental tertentu, yaitu kesiapan untuk berbagi (sharing), melepaskan sebagian pendapat, bahkan haknya untuk bisa menerima pendapat atau hak orang lain. Sikap yang ngotot, mau menang sendiri dan merasa benar sendiri, jelas bukan hal yang kondusif untuk mendengar aktif.
Kesiapan Mental
Dari pengalaman selama ini, kiranya sulit untuk dibantah bahwa kesiapan mental untuk berdialog antara lembaga eksekutif dan legislatif di negara kita masih jauh dari kenyataan. Istilah yang digunakan pun adalah “hearing” oleh DPR, bukan “listening”. Demikian pula DPR (DPRD) “memanggil” pemerintah (pemerintah daerah), persis seperti polisi memanggil tersangka. Sedangkan tata letak kursi-meja di ruang-ruang sidang komisi adalah sedemikian rupa sehingga ketua dan para wakil ketua, disertai para anggota duduk berhadapan dengan pemerintah (atau pihak lain yang didengar), persis sama dengan para hakim dan panitera, menghadapi terdakwa dan para saksi. Pendek kata, dalam tata-tertib hubungan pemerintah dan DPR, yang ada adalah hubungan a-simetris (DPR lebih tinggi dari pemerintah), bukan hubungan simetris (sejajar).
Hubungan a-simetris tidak selalu berarti jelek. Di lingkungan militer, dan perusahaan-perusahaan berteknologi tinggi yang menuntut zero error (misalnya: anjungan penambangan minyak, pesawat terbang atau kapal laut), dialog tetap bisa terjadi, walaupun pola komunikasinya a-simetris (tentunya melalui prosedur yang baku dan diberlakukan dengan sangat ketat). Syaratnya hanya satu: kedua pihak (atasan maupun bawahan) sama-sama menyadari peran dan posisinya masing-masing.
Masalahnya, anggota-anggota DPR kita, tidak siap untuk menerima peran dan posisi setara dalam komunikasi dialogis dengan pemerintah. Walaupun selalu kita dengar ucapan para politisi itu tentang kemitraan dan kesetaraan Pemerintah-DPR, yang ada justru pola komunikasi yang a-simetris seperti yang sudah diutarakan di atas.
Bahkan lebih memprihatinkan lagi, para anggota DPR ini tidak hanya menganggap pemerintah sebagai pihak yang statusnya lebih rendah, melainkan juga sesama anggota DPR sendiri. Itulah sebabnya sebulan pertama, DPR tidak bisa mulai bekerja, karena dua fraksi besar dalam DPR saling berselisih dan salah satu fraksi memilih untuk tidak masuk kantor saja selama sebulan. Lebih hebat lagi, pada saat membahas tentang kenaikan harga BBM, para anggota DPR bukannya saling adu argumentasi dengan pemerintah, tetapi malah saling berkelahi di antara mereka sendiri.
Tidak Siap Jadi Elit
Yang menarik, sebagian dari anggota DPR itu, beberapa saat sebelum dilantik adalah anggota masyarakat biasa. Ada yang artis, LSM, dosen, kiai dsb. Sebagai anggota masyarakat biasa, banyak (walaupun tidak semua) yang mempunyai reputasi yang baik: tidak punya track-record yang jelek, berintegritas, punya komitmen yang tinggi, pandangan-pandangannya mewakili pendapat rakyat dan seterusnya. Tetapi justru semuanya berubah setelah beliau-beliau menjadi anggota badan legislatif. Di daerah pun gejalanya sama.
Di lingkungan pemerintah (pusat maupun daerah), ternyata gejalanya tidak jauh berbeda. Kasus KPU misalnya, kalau pelanggaran pidananya benar terbukti, menunjukkan kepada kita betapa orang-orang berintegritas tinggi, bisa berubah sikap begitu masuk ke jajaran elite. Demikian pula halnya dengan para kepala daerah dan pejabat-pejabat daerah (tingkat propinsi maupun kabupaten) yang dikenal sebagai orang yang berintegritas tinggi, namun disuruh turun oleh rakyat begitu mereka menduduki jabatannya. Di tingkat partai politik, hampir tidak ada orang yang bisa terpilih menjadi ketua umum, tanpa menuai protes dari kelompok pesaingnya. Dan sikap yang diambil oleh yang menang maupun yang kalah adalah sikap konfrontatif (adu otot), karena memang rata-rata orang Indonesia masih lebih mengandalkan otot ketimbang hati sanubari.
Kesimpulannya, nampaknya watak bangsa Indonesia hanya baik jika mereka menjadi rakyat jelata, namun segera berubah ketika mereka masuk ke tingkat elit. Dengan perkataan lain, sebagian terbesar masayarakat Indonesia hanya siap jadi rakyat, tetapi tidak siap untuk menjadi elit. Begitu menjadi elit (apa pun, tidak hanya anggota DPR dan Pemerintah) maka akan terjadi perubahan mental yang signifikan. Karena itulah orang Indonesia lebih disiplin kalau dipimpin atau dimanajeri oleh seorang “bule”, ketimbang oleh pribumi sendiri.
Upaya
Menurut para pakar, ada dua macam jalan keluar dari komunikasi yang macet ini. Sebagian pakar (seperti John Naisbit, penulis buku “Milenium ke-Tiga”, dan Tu Weiming, Guru Besar Sejarah Agama-agama dari Universitas Harvard) berpendapat bahwa proses chaos ini akan berakhir sendiri, karena hanya merupakan bagian dari proses evolusi teknologi komunikasi dan informasi yang berskala jauh lebih besar, yang pada satu titik akan mencapai keseimbangan (equilibrium) sendiri secara alamiah (nilai baru, norma baru, tatanan masyarakat baru dsb. yang lebih adil, lebih manusiawi dsb.). Tetapi kapan saat itu akan tiba? Tidak ada yang bisa memastikan.
Pendapat kedua adalah dengan intervensi yang sistimatis dan terprogram. Paradigma inilah yang ditawarkan Suharto dulu, tatkala ia akan lengser. Dia menyatakan akan menata dulu pemerintahan selama 6 bulan ke depan, dan setelah itu ia tidak akan mencalonkan diri lagi menjadi presiden. Namun rupanya tawaran itu ditolak mentah-mentah oleh masyarakat yang sedang haus demokrasi. Pasalnya, memang intervensi atau social engineering menuntut pengorbanan, seperti: rakyat harus diatur dengan ketat, beberapa kebebasan ditarik dari masyarakat dsb. (seperti yang terjadi di Malaysia dan Singapura), padahal hal-hal yang harus dikorbankan itu, justru yang baru kita peroleh melalui reformasi dan pengorbanan jiwa. Maka terjadilah seperti yang kita alami sekarang.
Mana dari kedua strategi itu yang akan diikuti, kiranya akan sangat tergantung kepada kemampuan dan kemauan pemerintah, khususnya presiden dan wakilnya. Presiden dan wapres hasil Pemilu langsung sebenarnya mempunyai posisi yang sangat kuat dan tidak bisa begitu saja di dikte, apalagi di-impeach oleh DPR. Karena itu ia cukup punya legitimasi untuk menentukan pola permainan dan komunikasi politik yang akan berlaku. Kalau perlu dengan sedikit ketegasan. Gejolak pasti terjadi, tetapi tidak akan lama, karena kalau rakyat sudah melihat manfaatnya, maka protes akan berhenti dengan sendirinya (analoginya: Busway di DKI, awalnya sempat mengundang protes, tetapi sekarang hampir semua orang pernah menikmatinya, dan protes pun segera terhenti dengan sendirinya).
Namun kalau presiden masih tetap lebih suka mendengarkan dan mempertimbangkan suara-suara sumbang yang tidak habis-habisnya, termasuk dari golongan yang sudah jelas-jelas bersalah di mata hukum (seperti pedagang kaki lima, pengunjuk rasa yang membakar foto Presiden dsb.) demi demokrasi itu sendiri, maka memang kita tidak bisa mengharapkan banyak dari komunikasi-komunikasi antara DPR dan pemerintah di masa yang akan datang.




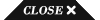

Post a Comment