Dalam Alquran, Allah Swt. berfirman antara lain bahwa Allah tidak menjadikan suatu kesempitan dalam agama dan hendak memberikan keringanan kepada manusia karena manusia mempunyai sifat lemah. Dari ayat Alquran tersebut, beberapa ulama menafsirkan bahwa Allah Swt menjadikan agama Islam sebagai agama yang mudah dan tidak menyulitkan hamba-Nya untuk melaksanakan perintah atau menjauhi larangan-Nya.
Pada dasarnya, Allah Swt. tidak mungkin memberikan perintah dan larangan manakala tidak bisa dilaksanakan oleh hamba-Nya. Para ulama ushul fikih berkesimpulan bahwa hukum yang ditetapkan oleh Allah Swt. memiliki keniscayaan untuk bisa dilaksanakan oleh mukalaf dan tidak mengandung unsur kesukaran berlebih.
Namun jika keadaan mukalaf itu lemah dan tidak dapat melaksanakan hukum tersebut maka Allah swt telah menyiapkan perangkat hukum lanjutan yang di dalamnya penuh kemudahan (al-taysîr) dan keringanan (al-takhfîf). Inilah yang kemudian disebut rukhsah. Saat ini, dalam memandang hukum yang ditetapkan oleh Allah Swt., kaum Muslim terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah kaum Muslim yang menitikberatkan permasalahan hukum hanya pada permasalahan hukum asli dan menafikan hukum lanjutan yang meringankan para mukalaf. Mereka cenderung fanatik, kaku, dan tidak memahami ruh syariah (maqâshid al-syarî’ah). Dan ini sangat bertentangan dengan Hadis Rasulullah Saw yang diriwayatkan Imâm Ahmad, ketika beliau ditanya tentang agama yang dicintai oleh Allah, Rasulullah Saw. menjawab yaitu al-hanîfiyyah al-samhah, yang maknanya adalah lembut, lentur, tidak kaku, dan toleran.
Kelompok kedua adalah kaum Muslim yang hanya melihat permasalahan hukum lanjutan. Mereka adalah kaum yang hanya menginginkan keringanan, kemudahan, dan tidak ingin bersusah payah. Kelompok ini cenderung menggampangkan hukum (al-mutasâhilûn fî al-ahkâm), bahkan cenderung meremehkan. Di dalam kajian ilmu fikih dan ushul fikih, hukum yang dimaksud adalah hukum taysîr yang meliputi hukum asli dan hukum lanjutan.
BAB II
ISI
Konsep Taysîr dan Relasinya dengan Hukum Taklif
Secara etimologi, taysîr berasal dari kata “yasara” yang berarti lembut, lentur, mudah, fleksibel, tertib, dan dapat digerakan, atau anonim dari kata ‘usr yaitu kesulitan.Para ulama ushul fikih berpendapat bahwa taysîr adalah menjadikan segala sesuatu itu mudah dan dapat dikerjakan serta tidak menyulitkan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt bahwa “Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran”.
Menurut terminologi, Manshûr Muhammad Manshûr al-Hafnawî berpendapat bahwa taysîr adalah perihal yang abstrak dan memiliki penilaian yang relatif. Taysîr terkadang diartikan sebagai sesuatu yang memberikan keleluasaan kepada mukalaf dalam melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, dan terkadang mengeluarkan mukalaf dari kesukaran pada kemudahan untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan tersebut. Menurut ‘Abd al-‘Azîz Muhammad Azam, taysîr adalah pelegalan hukum berdasarkan kemampuan mukalaf untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan tanpa beban dan kesukaran yang menghalanginya. Sedangkan Shâlih ibn ‘Abd Allâh ibn Hâmid merumuskan bahwa taysîr adalah kemudahan dan keleluasaan yang lazimnya diutamakan oleh mukalaf tanpa menemui beban dan kesulitan yang berlebih, serta mukalaf dapat mengerjakannya tanpa mengeluarkan usaha yang berlebih dari kemampuan yang dimilikinya.
Baik secara etimologi maupun terminologi, pada hakikatnya yang dimaksud dengan taysîr adalah hukum taklif yang diberikan oleh al-syâri’ (regulator) kepada mukalaf untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan dengan ketentuan tidak ada kesukaran yang membebaninya dan adanya kemudahan yang memberikan keleluasaan kepada mukalaf untuk mengerjakannya. Relatifitas taysîr ini juga diungkap oleh ‘Abd al-‘Azîz Muhammad ‘Azam yang berpendapat bahwa taysîr terkadang ada pada hukum asli dan terkadang ada ketika hukum asli memiliki kesukaran untuk diterapkan, sehingga lahirlah taysîr dalam bentuk keringanan (al-takhfîf) dan menghilangkan kesukaran (raf’ al-haraj).
Namun jika itu memberatkan maka berlakulah perubahan hukum tersebut. Contoh hal ini dapat ditemukan pada hukum asli yaitu Allah Swt. mewajibkan mukalaf untuk shalat dengan berdiri, namun jika mukalaf memiliki kesukaran untuk melaksanakannya maka berlakulah perubahan hukum asli tersebut dalam bentuk keringanan atau rukhsah sehingga dalam hal ini mukalaf boleh shalat dengan duduk. Adapun materi yang memiliki kemiripan dengan taysîr yaitu: pertama, keringanan atau rukhsah (dalam bahasa Arab rukhshah). Secara etimologi, “rukhshah” berasal dari kata “rakhasha” yang berarti kemudahan, kelenturan, kemurahan, izin, dan anonim dari kekerasan atau kekakuan. Untuk memahami makna rukhsah tersebut, Jamâl al-Dîn Muhammad ibn Manzhûr memberikan contoh bahwa jika Allah Swt memberikan rukhsah bagi mukalaf yang memiliki uzur syar’î pada suatu perkara, hal ini berarti Allah Swt memberikan keringanan pada perkara tersebut dan mengizinkan mukalaf untuk meninggalkannya. Sedangkan rukhsah menurut istilah adalah hukum pengecualian yang dilegalkan oleh Allah Swt. dan bertentangan dengan hukum aslinya berdasarkan uzur syar’î yang memberatkan mukalaf untuk melaksanakan perintah atau menjauhi larangan dari perkara-perkara yang ditetapkan. Jika ditelusuri lebih dalam, para ulama ushul fikih memiliki perbedaan definisi rukhsah. Para ulama hanafiyyah mendefinisikan rukhsah sebagai perkara hukum yang telah ditetapkan atas dasar halangan-halangan yang ditemui oleh mukalaf atau perkara hukum yang diperkenankan untuk dilakukan atas dasar uzur syar’î dengan dalil syar’î yang diharamkannya.Ulama mâlikiyyah mendefinisikan rukhsah sebagai perkara hukum yang ditetapkan dengan uzur syar’î. Imâm Syâthibî menguraikan bahwa rukhsah adalah perkara hukum yang ditetapkan atas dasar pengecualian dari hukum aslinya, dimana mukalaf tidak mampu untuk mengerjakannya. Ulama syâfi’iyyah berpendapat bahwa rukhsah adalah perkara hukum yang ditetapkan berdasarkan dalil yang bertentangan dari dalil hukum aslinya yang disebabkan oleh uzur syar’î.
Sedangkan al-Âmidî berpendapat bahwa rukhsah adalah perkara hukum yang diperkenankan disebabkan oleh faktor-faktor yang diharamkan. Dan ulama hanâbilah tidak jauh berbeda mendefinisikan rukhsah dari ulama syâfi’iyyah, akan tetapi ulama hanâbilah memberikan penguat dalil Alquran, yaitu “Maka siapa saja yang terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” Adapun perbedaan taysîr dengan rukhsah dapat disimpulkan sebagai berikut:
(1) Taysîr adalah hukum asli yang ditetapkan oleh dalil pertama, seperti diwajibkannya sholat 5 waktu dalam syariat Nabi Muhammad Saw. Sedangkan rukhsah adalah hukum pengecualian yang ditetapkan berdasarkan dalil parsial yang bertentangan dengan dalil asli berdasarkan uzur syar’î, seperti diperkenankannya shalat jamak bagi mukalaf yang memiliki uzur syar’î seperti sakit dan dalam perjalanan.
(2) Rukhsah selalu bertentangan dengan hukum asli yang telah ditetapkan, sedangkan taysîr adalah hukum asli (‘azîmah) itu sendiri ataupun hukum pengecualian (rukhsah), dengan catatan bahwa setiap rukhsah adalah taysîr, akan tetapi tidak semua taysîr adalah rukhsah.
(3) Taysîr adalah hukum asli (‘azîmah) dan juga hukum yang mendapat keringanan (rukhsah), sedangkan rukhsah adalah hukum pengecualian yang bertentangan dengan hukum asli (‘azîmah).
(4) Rukhsah adalah perkara hukum yang berdasarkan taysîr (keringanan, kemudahan, dan kelenturan) yang ditetapkan untuk meringankan mukalaf dari perkara yang menyulitkan, sedangkan taysîr adalah hukum asli (‘azîmah) yang disyariatkan.
Kedua, menghilangkan kesukaran (raf’ al-haraj). Raf’ al-haraj terdiri atas dua kata, yaitu kata raf’ yang berarti mengurangi, mencapai, membawa, mendekati dan menghilangkan perkara. Di dalam kamus Lisân al-‘Arab, raf’ adalah pergerakan, perpindahan, dan tidak adanya beban terhadap mukalaf. Hal ini sesuai Hadis Rasulullah Saw. “Tiga perkara yang tidak dibebankan kepada mukalaf, yaitu kepada orang yang tidur hingga bangun, kepada anak hingga dewasa, dan kepada orang yang tidak berakal hingga kembali akalnya”. Dan kata al-haraj yang berarti kesempitan dan kesukaran.
Dengan demikian, yang dimaksud raf’ al-haraj adalah menghilangkan kesempitan (izâlah al-dhayq) dan mengangkat/memindahkan dari tempatnya. Adapun secara terminologi, Shâlih ibn ‘Abd Allâh ibn Hâmid menjelaskan bahwa al-haraj adalah segala sesuatu yang memberatkan dan memberikan kesukaran yang berlebih kepada mukalaf, baik itu berada di jiwa, raga, atau harta. Dengan demikian, raf’ al-haraj adalah menghilangkan segala sesuatu dari beban dan kesukaran yang berlebih, serta memberikan kemudahan/keringanan (al-taysîr) bagi mukalaf untuk menghindarinya. Adapun perbedaan taysîr dan raf’ al-haraj dapat disimpulkan sebagai berikut:
(1) Taysîr adalah hukum asli yang dibebankan kepada mukalaf, baik kesukaran terkandung di dalamnya atau tidak. Sedangkan raf’ al-haraj adalah hukum yang terkadang mengandung keringanan (taysîr) yang disyariatkan oleh Allah Swt. kepada umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad Saw., dan terkadang menjadi hukum parsial dari hukum yang ditetapkan dan memiliki kesukaran.
(2) Raf’ al-haraj diberlakukan manakala terdapat ketakutan dari kerusakan yang dilakukan mukalaf di dalam jiwa, raga, harta, akal, dan keadaannya. Sedangkan taysîr adalah sebaliknya.
(3) Raf’ al-haraj ada setelah kesukaran atau kesempitan itu terjadi pada suatu perkara yang dibebankan kepada mukalaf. Sedangkan taysîr ditetapkan sebagai hukum dan bukan dalam rangka untuk membebani mukalaf dari kesukaran berlebih dan kesempitan.
(4) Raf’ al-haraj adalah perihal hukum yang dikhususkan untuk menghilangkan kesukaran berlebih. Sedangkan taysîr adalah hukum yang bersifat umum.
Ketiga, kesukaran (al-masyaqqah). Menurut Ya’qûb al-Bahusayn, masyaqqah adalah suatu keadaan yang sukar, dimana mukalaf tidak dapat memikulnya, baik secara sebagian atau seluruhnya, akibat ketidaksempurnaan keadaan jiwa, raga, harta, keadaan, dan kondisi mukalaf. Masyaqqah yang dimaksudkan adalah kesukaran yang bukan pada umumnya (al-masyaqqah ghayr al-mu’tâdah) dan menyebabkan mukalaf tidak dapat memikul bebannya. Dalam syariat, kesukaran ini mendapat keringanan (al-takhfîf). Sedangkan kesukaran yang umum (al-masyaqqah al-mu’tâdah) adalah kesukaran yang tidak memberatkan mukalaf, sehingga meskipun di setiap perintah dan larangan terdapat kesukaran, maka kesukaran ini umum dan dapat dipikul oleh mukalaf. Dalam syariat, kesukaran ini tidak mendapatkan keringanan. Berangkat dari penjelasan masyaqqah di atas, maka semangat taysîr sangat bertolak belakang dengan kesukaran yang bukan pada umumnya, sedangkan di dalam kesukaran yang umum, taysîr berada di dalamnya.
Kedudukan Taysîr dalam Hukum Taklif
Ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk diberlakukannya hukum taklif kepada mukalaf adalah:
1. Syarat yang berkenaan dengan mukalaf, yaitu mukalaf dalam keadaan hidup, mukalaf adalah manusia, dan bukan hewan ataupun tumbuhan, mukalaf harus sudah baligh, berakal, memahami perintah dan larangan, memiliki kemampuan untuk memilih, memiliki kecakapan untuk melaksanakan, dan beragama Islam.
2. Syarat yang berkenaan dengan beban perintah dan larangan yang ditujukan kepada mukalaf, yaitu objek perintah dan larangan harus belum terlaksana, objek perintah dan larangan harus merupakan hasil dari perbuatan mukalaf sendiri, objek perintah dan larangan harus diketahui oleh mukalaf, objek perintah dan larangan harus sesuai dengan syariat, dan objek perintah dan larangan haruslah sesuai dengan kemampuan mukalaf.
Sedangkan kedudukan hukum taysîr dalam hukum taklif terbagi dua, yaitu: pertama, kedudukan hukum taysîr pada objek perintah dan larangan yang dapat dipikul oleh mukalaf, baik dalam ibadah maupun mumalat. Imâm al-Syâthibî menjelaskan bahwa pada hakikatnya, objek perintah dan larangan pasti mengandung unsur kesukaran, namun kesukaran semacam ini adalah kesukaran lazim yang dapat dibebankan. Inilah yang dimaksud dengan kesukaran (al-masyaqqah) sesungguhnya. Ibn ‘Abd al-Salâm memberikan contoh seperti hakikat air dingin yang digunakan saat wudhu atau mandi adalah kesukaran yang lazim dan umumnya dapat dikerjakan oleh mukalaf. Dalam hal ini, Allah Swt. telah memberikan hakikat taysîr ke dalam objek perintah dan larangan, sehingga hukum taklif tersebut tidak dapat dikurangi atau dihilangkan dari pembebanan kepada mukalaf dengan alasan kesukaran.
Kedua, kedudukan hukum taysîr pada objek perintah dan larangan yang tidak dapat dipikul oleh mukalaf, yaitu objek pekerjaan yang memiliki kesukaran berlebih dan sangat mustahil untuk dikerjakan oleh mukalaf. Para ulama ushul fikih memberikan contoh bahwa mustahil bagi mukalaf untuk mengerjakan dua perintah yang bertentangan di satu waktu tertentu. Atau objek pekerjaan yang memiliki kesukaran berlebih akan tetapi mukalaf dapat mengerjakannya dengan sekuat tenaga dan mempertaruhkan jiwa, seperti perintah puasa bagi mukalaf yang sakit keras. Dalam hal ini, Allah Swt. memberikan rahmat-Nya dengan meringankan perintah tersebut ke dalam hukum taysîr, dalam hal ini adalah rukhsah.
Taysîr dan Sistem Ekonomi Islam
Sejatinya, hukum Islam yang telah ditetapkan oleh Allah Swt., baik itu yang berkenaan dengan ibadah maupun muamalat, sudah sangat sempurna dan menyeluruh, sehingga permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh mukalaf dapat dikaji langsung dari Alquran dan Sunah Rasul-Nya. Hal ini sesuai dengan firmanNya, yaitu “Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu, cukupkan nikmat-Ku kepadamu, dan telah Aku ridhai Islam itu menjadi agama bagimu”. Berkaitan dengan taysîr, pada hakikatnya Allah Swt. telah melandasi hukum yang ditetapkan dengan unsur taysîr, baik dalam hukum asli (al-‘azîmah) ataupun hukum lanjutan (al-rukhshah).
Hal ini dikarenakan Allah Swt. mengetahui bahwa manusia sebagai mukalaf (terutama umat Nabi Muhammad Saw.) sangat membutuhkan sesuatu yang mudah dan meringankan dalam melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-Nya. Syariat yang ditetapkan oleh Allah Swt. kepada umat terdahulu berbeda dengan umat Nabi Muhammad Saw., misalnya dahulu sholat dilaksanakan 50 kali dalam satu hari, sedangkan umat Nabi Muhammad Saw. hanya melaksanakan 5 kali sholat fardu dalam satu hari. Muhammad Sa’ad al-Yûbî, menguraikan bahwa kesejatian Allah Swt. menjadikan syariat Nabi Muhammad Saw. mudah dan ringan adalah dalam rangka memberikan kemaslahatan dalam ibadah dan muamalat.
Dengan kata lain, kesejatian itu terletak di mukalaf yang membutuhkan kemudahan dan keringan. Secara logika, bagaimana mungkin Allah Swt. yang memiliki sifat pengasih lagi penyayang mempersulit dan membebani hamba-Nya, serta menyeru untuk beribadah namun memberikan kesulitan yang menghalangi mereka untuk dapat melaksanakan perintah tersebut. Ibn ‘Abd al-Salâm menegaskan bahwa sesungguhnya segala yang dikerjakan mukalaf adalah dalam rangka untuk taat, patuh, dan mendekatkan diri kepada Allah Swt., sehingga dikatakan bagaimana mungkin Allah Swt. menyulitkan hamba-Nya untuk taat, patuh, dan dekat kepada-Nya. Dalam hal ini, diberlakukanlah kemudahan dan keringanan bagi hamba-hamba-Nya. Imâm al-Syâthibî juga menegaskan bahwa dalam penerapan syariat tidak ada hal yang memberatkan dan menyulitkan sehingga mukalaf terbebani.
Di dalam sistem ekonomi Islam, para ekonom Muslim dan ulama fikih sepakat menyatakan bahwa aturan, prinsip, hukum, dan etika bermuara pada syariat yang diberikan oleh Allah Swt. kepada Rasulullah Saw. dan umatnya dalam bentuk teks dan maknawi yang terkandung di dalam Alquran dan Sunah. Syariat yang Allah Swt. berikan kepada umat Nabi Muhammad Saw. adalah syariat yang lengkap, dimana tidak mengandung kesukaran yang berarti dan bahkan terkandung di dalamnya kemudahan (al-taysîr) yang memungkinkan seorang mukalaf dapat melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-Nya.
Dalam sistem ekonomi Islam, misalnya, ada pembahasan mengenai kewajiban bekerja bagi kaum Muslim untuk memenuhi kebutuhan hidup, mendukung kegiatan ibadah, dan memenuhi hak orang lain yang di bawah tanggungannya. Kewajiban ini adalah perintah Allah Swt., yaitu “Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan” dan “Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain”. Rasulullah Saw. juga bersabda bahwa “Tidak seorang Muslim pun yang menanam tanaman, lalu dimakan oleh seekor burung atau manusia dan hewan, kecuali merupakan bentuk sedekah baginya”.
Dalam perintah bekerja ini, Allah Swt. tidak membatasi pekerjaan apa yang harus dilakukan mukalaf, bahkan memberikan keleluasaan bekerja. Namun demikian, Allah Swt. memberikan catatan bagi mukalaf bahwa pekerjaan mukalaf harus halal dan materi yang didapatkan dari hasil bekerja itu juga harus halal dan baik. Dari sistem ekonomi Islam di atas, dapat dicermati bahwa perintah bekerja yang diwajibkan oleh Allah Swt. kepada kaum Muslim tidak mengandung kesukaran yang berlebih. Hal ini dapat dilihat manakala Allah Swt. memberikan keleluasaan bagi mukalaf untuk dapat bekerja di bidang apapun, sehingga mukalaf dapat menyesuaikan kemampuannya dengan perintah Allah Swt. Bagi yang mampu berniaga, maka diperkenankan untuk bekerja dalam hal perniagaan. Bagi yang mampu bekerja di instansi, maka diperkenankan untuk bekerja di dalamnya. Jika tidak mengandung kesukaran berlebih, maka ini adalah kemudahan yang memberikan kemaslahatan bagi manusia tersebut. Meskipun di dalam perintah bekerja Allah Swt. memberikan catatan agar mukalaf bekerja di sektor yang halal dan memakan materi yang didapat dari bekerja itu adalah halal dan baik. Namun demikian, hal ini bukanlah kesukaran berlebih yang dimaksud sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Imâm al-Syâthibî di atas.
Dalam jual beli misalnya, Allah Swt. dan Nabi Muhammad Saw. tidak membatasi kaum Muslim untuk bertransaksi dengan kaum non-Muslim dan materi yang ditransaksikan juga diberikan keleluasaan. Batasan yang diberikan hanya masalah kehalalannya. Dalam hadis disebutkan: Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya melarang orang memperjualbelikan arak, bangkai, babi, dan patung-patung. Maka seorang dari sahabat bertanya: “Ya Rasulullah, tahukah kamu bahwa lemak bangkai digunakan untuk mengecat kapal dan meminyaki kulit dan untuk lampu penerangan?”. Rasulullah Saw. menjawab: “Semua itu tetap haram...”. Dalam riwayat lain disebutkan,Rasulullah Saw. bersabda: “Dua orang yang berjual beli berhak khiyâr (saling tawar menawar) selama belum berpisah. Jika mereka berlaku jujur dan berterus terang, diberkahilah jual beli mereka. Tetapi jika tidak berterus terang dan berbohong, dihapuskanlah berkah jual beli mereka.” (H.r. al-Bukhârî).
Berdasarkan beberapa ayat Alquran dan Hadis, dapat dicermati bahwa Allah Swt. tidak membebani mukalaf dengan kesukaran yang berlebih. Bahkan Allah Swt. dan Rasul-Nya memberikan contoh kemudahan (al-taysîr) dan keleluasaan kepada kaum Muslim dalam bertransaksi dengan kaum non-Muslim. Sesuatu yang akan sangat menyulitkan jika kaum Muslim bertransaksi/jual-beli hanya kepada sesama kaum Muslim. Akan tetapi hal ini tidak diberlakukan oleh Allah Swt., mengingat jual-beli mengandung kemaslahatan bagi semua manusia.
Penerapan Taysîr dalam Sistem Ekonomi Islam
Ya’qûb al-Bahusayn menjelaskan bahwa salah satu dari faktor diperkenankannya kemudahan (al-taysîr) adalah adanya kesukaran (al’usr) dan keumuman permasalahan yang sering terjadi (‘umûm al-balwâ).
Dalam kegiatan ekonomi, terkadang ada kesukaran yang sering dihadapi oleh para pihak yang bertransaksi, seperti kesukaran untuk bertemu dan bertransaksi face to face. Padahal adanya pertemuan dalam bertransaksi merupakan sesuatu yang telah diisyaratkan oleh Rasulullah Saw. Maka dalam hal ini, banyak ulama fikih yang berpendapat bahwa untuk menghilangkan kesukaran tersebut diperkenankan para pihak menggunakan media telekomunikasi seperti telepon, sms, atau internet, sehingga syarat bertemu dan bertransaksi face to face yang tersirat dalam Hadis tersebut terpenuhi.
Adapun keumuman permasalahan yang sering terjadi (‘umûm al-balwâ) dan selalu ditemukan adalah seperti terbungkusnya komoditi yang diperjualbelikan sehingga menyulitkan seorang pembeli untuk mengetahui keadaan fisik komoditi tersebut. Dalam hal ini, para ulama fikih berpendapat bahwa untuk menghilangkan keumuman permasalahan yang sering terjadi dan selalu ditemukan adalah dengan membuka salah satu pembungkus komoditi tersebut untuk dijadikan contoh, sehingga seseorang yang akan membelinya dapat mengetahui kondisi fisik komoditi tersebut.
Penerapan konsep taysîr dalam sistem ekonomi Islam dihadirkan dalam rangka untuk memberi kemudahan, keringanan, dan kemaslahatan bagi para mukalaf. Baik di dalam hukum asli (al-‘azîmah) maupun hukum lanjutan (al-rukhshah) yang berkenaan dengan sistem ekonomi Islam. Taysîr dihadirkan oleh Allah Swt untuk memberi kemaslahatan dan kemudahan bagi manusia, sehingga tidak ada alasan bagi manusia untuk tidak menjalankan perintah dan menjauhi larangan-Nya, terutama yang berkenaan dengan kegiatan bisnis dan ekonomi.
Saat ini, dunia perbankan syariah dan industri syariah yang berkembang pesat, sangat membutuhkan perangkat hukum dalam rangka untuk menciptakan produk dan inovasi kreatif, sebagai konsekuensi tuntutan zaman dan kebutuhan manusia yang terus berkembang. Konsep hukum taysîr sangat dimungkinkan untuk menjawab kebutuhan di atas. Konsep ini sangat mencerminkan kemudahan dan kelenturan agama Islam, serta ketegasannya di dalam menjawab tantangan zaman.
Namun demikian, penerapan konsep ini tidak serta-merta dibenarkan tanpa memperhatikan maksud Allah Swt melegalkan hukum (maqashid al-syarî’ah), terutama dalam hal menjaga harta. Hal ini dilakukan untuk menjaga mukalaf tetap patuh dan taat dengan syariat yang telah ditentukan dan terhindar dari perbuatan yang meremehkan atau menggampangkan hukum (al-mutasâhilûn fî al-ahkâm).
Pada dasarnya, Allah Swt. tidak mungkin memberikan perintah dan larangan manakala tidak bisa dilaksanakan oleh hamba-Nya. Para ulama ushul fikih berkesimpulan bahwa hukum yang ditetapkan oleh Allah Swt. memiliki keniscayaan untuk bisa dilaksanakan oleh mukalaf dan tidak mengandung unsur kesukaran berlebih.
Namun jika keadaan mukalaf itu lemah dan tidak dapat melaksanakan hukum tersebut maka Allah swt telah menyiapkan perangkat hukum lanjutan yang di dalamnya penuh kemudahan (al-taysîr) dan keringanan (al-takhfîf). Inilah yang kemudian disebut rukhsah. Saat ini, dalam memandang hukum yang ditetapkan oleh Allah Swt., kaum Muslim terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah kaum Muslim yang menitikberatkan permasalahan hukum hanya pada permasalahan hukum asli dan menafikan hukum lanjutan yang meringankan para mukalaf. Mereka cenderung fanatik, kaku, dan tidak memahami ruh syariah (maqâshid al-syarî’ah). Dan ini sangat bertentangan dengan Hadis Rasulullah Saw yang diriwayatkan Imâm Ahmad, ketika beliau ditanya tentang agama yang dicintai oleh Allah, Rasulullah Saw. menjawab yaitu al-hanîfiyyah al-samhah, yang maknanya adalah lembut, lentur, tidak kaku, dan toleran.
Kelompok kedua adalah kaum Muslim yang hanya melihat permasalahan hukum lanjutan. Mereka adalah kaum yang hanya menginginkan keringanan, kemudahan, dan tidak ingin bersusah payah. Kelompok ini cenderung menggampangkan hukum (al-mutasâhilûn fî al-ahkâm), bahkan cenderung meremehkan. Di dalam kajian ilmu fikih dan ushul fikih, hukum yang dimaksud adalah hukum taysîr yang meliputi hukum asli dan hukum lanjutan.
BAB II
ISI
Konsep Taysîr dan Relasinya dengan Hukum Taklif
Secara etimologi, taysîr berasal dari kata “yasara” yang berarti lembut, lentur, mudah, fleksibel, tertib, dan dapat digerakan, atau anonim dari kata ‘usr yaitu kesulitan.Para ulama ushul fikih berpendapat bahwa taysîr adalah menjadikan segala sesuatu itu mudah dan dapat dikerjakan serta tidak menyulitkan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt bahwa “Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran”.
Menurut terminologi, Manshûr Muhammad Manshûr al-Hafnawî berpendapat bahwa taysîr adalah perihal yang abstrak dan memiliki penilaian yang relatif. Taysîr terkadang diartikan sebagai sesuatu yang memberikan keleluasaan kepada mukalaf dalam melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, dan terkadang mengeluarkan mukalaf dari kesukaran pada kemudahan untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan tersebut. Menurut ‘Abd al-‘Azîz Muhammad Azam, taysîr adalah pelegalan hukum berdasarkan kemampuan mukalaf untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan tanpa beban dan kesukaran yang menghalanginya. Sedangkan Shâlih ibn ‘Abd Allâh ibn Hâmid merumuskan bahwa taysîr adalah kemudahan dan keleluasaan yang lazimnya diutamakan oleh mukalaf tanpa menemui beban dan kesulitan yang berlebih, serta mukalaf dapat mengerjakannya tanpa mengeluarkan usaha yang berlebih dari kemampuan yang dimilikinya.
Baik secara etimologi maupun terminologi, pada hakikatnya yang dimaksud dengan taysîr adalah hukum taklif yang diberikan oleh al-syâri’ (regulator) kepada mukalaf untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan dengan ketentuan tidak ada kesukaran yang membebaninya dan adanya kemudahan yang memberikan keleluasaan kepada mukalaf untuk mengerjakannya. Relatifitas taysîr ini juga diungkap oleh ‘Abd al-‘Azîz Muhammad ‘Azam yang berpendapat bahwa taysîr terkadang ada pada hukum asli dan terkadang ada ketika hukum asli memiliki kesukaran untuk diterapkan, sehingga lahirlah taysîr dalam bentuk keringanan (al-takhfîf) dan menghilangkan kesukaran (raf’ al-haraj).
Namun jika itu memberatkan maka berlakulah perubahan hukum tersebut. Contoh hal ini dapat ditemukan pada hukum asli yaitu Allah Swt. mewajibkan mukalaf untuk shalat dengan berdiri, namun jika mukalaf memiliki kesukaran untuk melaksanakannya maka berlakulah perubahan hukum asli tersebut dalam bentuk keringanan atau rukhsah sehingga dalam hal ini mukalaf boleh shalat dengan duduk. Adapun materi yang memiliki kemiripan dengan taysîr yaitu: pertama, keringanan atau rukhsah (dalam bahasa Arab rukhshah). Secara etimologi, “rukhshah” berasal dari kata “rakhasha” yang berarti kemudahan, kelenturan, kemurahan, izin, dan anonim dari kekerasan atau kekakuan. Untuk memahami makna rukhsah tersebut, Jamâl al-Dîn Muhammad ibn Manzhûr memberikan contoh bahwa jika Allah Swt memberikan rukhsah bagi mukalaf yang memiliki uzur syar’î pada suatu perkara, hal ini berarti Allah Swt memberikan keringanan pada perkara tersebut dan mengizinkan mukalaf untuk meninggalkannya. Sedangkan rukhsah menurut istilah adalah hukum pengecualian yang dilegalkan oleh Allah Swt. dan bertentangan dengan hukum aslinya berdasarkan uzur syar’î yang memberatkan mukalaf untuk melaksanakan perintah atau menjauhi larangan dari perkara-perkara yang ditetapkan. Jika ditelusuri lebih dalam, para ulama ushul fikih memiliki perbedaan definisi rukhsah. Para ulama hanafiyyah mendefinisikan rukhsah sebagai perkara hukum yang telah ditetapkan atas dasar halangan-halangan yang ditemui oleh mukalaf atau perkara hukum yang diperkenankan untuk dilakukan atas dasar uzur syar’î dengan dalil syar’î yang diharamkannya.Ulama mâlikiyyah mendefinisikan rukhsah sebagai perkara hukum yang ditetapkan dengan uzur syar’î. Imâm Syâthibî menguraikan bahwa rukhsah adalah perkara hukum yang ditetapkan atas dasar pengecualian dari hukum aslinya, dimana mukalaf tidak mampu untuk mengerjakannya. Ulama syâfi’iyyah berpendapat bahwa rukhsah adalah perkara hukum yang ditetapkan berdasarkan dalil yang bertentangan dari dalil hukum aslinya yang disebabkan oleh uzur syar’î.
Sedangkan al-Âmidî berpendapat bahwa rukhsah adalah perkara hukum yang diperkenankan disebabkan oleh faktor-faktor yang diharamkan. Dan ulama hanâbilah tidak jauh berbeda mendefinisikan rukhsah dari ulama syâfi’iyyah, akan tetapi ulama hanâbilah memberikan penguat dalil Alquran, yaitu “Maka siapa saja yang terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” Adapun perbedaan taysîr dengan rukhsah dapat disimpulkan sebagai berikut:
(1) Taysîr adalah hukum asli yang ditetapkan oleh dalil pertama, seperti diwajibkannya sholat 5 waktu dalam syariat Nabi Muhammad Saw. Sedangkan rukhsah adalah hukum pengecualian yang ditetapkan berdasarkan dalil parsial yang bertentangan dengan dalil asli berdasarkan uzur syar’î, seperti diperkenankannya shalat jamak bagi mukalaf yang memiliki uzur syar’î seperti sakit dan dalam perjalanan.
(2) Rukhsah selalu bertentangan dengan hukum asli yang telah ditetapkan, sedangkan taysîr adalah hukum asli (‘azîmah) itu sendiri ataupun hukum pengecualian (rukhsah), dengan catatan bahwa setiap rukhsah adalah taysîr, akan tetapi tidak semua taysîr adalah rukhsah.
(3) Taysîr adalah hukum asli (‘azîmah) dan juga hukum yang mendapat keringanan (rukhsah), sedangkan rukhsah adalah hukum pengecualian yang bertentangan dengan hukum asli (‘azîmah).
(4) Rukhsah adalah perkara hukum yang berdasarkan taysîr (keringanan, kemudahan, dan kelenturan) yang ditetapkan untuk meringankan mukalaf dari perkara yang menyulitkan, sedangkan taysîr adalah hukum asli (‘azîmah) yang disyariatkan.
Kedua, menghilangkan kesukaran (raf’ al-haraj). Raf’ al-haraj terdiri atas dua kata, yaitu kata raf’ yang berarti mengurangi, mencapai, membawa, mendekati dan menghilangkan perkara. Di dalam kamus Lisân al-‘Arab, raf’ adalah pergerakan, perpindahan, dan tidak adanya beban terhadap mukalaf. Hal ini sesuai Hadis Rasulullah Saw. “Tiga perkara yang tidak dibebankan kepada mukalaf, yaitu kepada orang yang tidur hingga bangun, kepada anak hingga dewasa, dan kepada orang yang tidak berakal hingga kembali akalnya”. Dan kata al-haraj yang berarti kesempitan dan kesukaran.
Dengan demikian, yang dimaksud raf’ al-haraj adalah menghilangkan kesempitan (izâlah al-dhayq) dan mengangkat/memindahkan dari tempatnya. Adapun secara terminologi, Shâlih ibn ‘Abd Allâh ibn Hâmid menjelaskan bahwa al-haraj adalah segala sesuatu yang memberatkan dan memberikan kesukaran yang berlebih kepada mukalaf, baik itu berada di jiwa, raga, atau harta. Dengan demikian, raf’ al-haraj adalah menghilangkan segala sesuatu dari beban dan kesukaran yang berlebih, serta memberikan kemudahan/keringanan (al-taysîr) bagi mukalaf untuk menghindarinya. Adapun perbedaan taysîr dan raf’ al-haraj dapat disimpulkan sebagai berikut:
(1) Taysîr adalah hukum asli yang dibebankan kepada mukalaf, baik kesukaran terkandung di dalamnya atau tidak. Sedangkan raf’ al-haraj adalah hukum yang terkadang mengandung keringanan (taysîr) yang disyariatkan oleh Allah Swt. kepada umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad Saw., dan terkadang menjadi hukum parsial dari hukum yang ditetapkan dan memiliki kesukaran.
(2) Raf’ al-haraj diberlakukan manakala terdapat ketakutan dari kerusakan yang dilakukan mukalaf di dalam jiwa, raga, harta, akal, dan keadaannya. Sedangkan taysîr adalah sebaliknya.
(3) Raf’ al-haraj ada setelah kesukaran atau kesempitan itu terjadi pada suatu perkara yang dibebankan kepada mukalaf. Sedangkan taysîr ditetapkan sebagai hukum dan bukan dalam rangka untuk membebani mukalaf dari kesukaran berlebih dan kesempitan.
(4) Raf’ al-haraj adalah perihal hukum yang dikhususkan untuk menghilangkan kesukaran berlebih. Sedangkan taysîr adalah hukum yang bersifat umum.
Ketiga, kesukaran (al-masyaqqah). Menurut Ya’qûb al-Bahusayn, masyaqqah adalah suatu keadaan yang sukar, dimana mukalaf tidak dapat memikulnya, baik secara sebagian atau seluruhnya, akibat ketidaksempurnaan keadaan jiwa, raga, harta, keadaan, dan kondisi mukalaf. Masyaqqah yang dimaksudkan adalah kesukaran yang bukan pada umumnya (al-masyaqqah ghayr al-mu’tâdah) dan menyebabkan mukalaf tidak dapat memikul bebannya. Dalam syariat, kesukaran ini mendapat keringanan (al-takhfîf). Sedangkan kesukaran yang umum (al-masyaqqah al-mu’tâdah) adalah kesukaran yang tidak memberatkan mukalaf, sehingga meskipun di setiap perintah dan larangan terdapat kesukaran, maka kesukaran ini umum dan dapat dipikul oleh mukalaf. Dalam syariat, kesukaran ini tidak mendapatkan keringanan. Berangkat dari penjelasan masyaqqah di atas, maka semangat taysîr sangat bertolak belakang dengan kesukaran yang bukan pada umumnya, sedangkan di dalam kesukaran yang umum, taysîr berada di dalamnya.
Kedudukan Taysîr dalam Hukum Taklif
Ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk diberlakukannya hukum taklif kepada mukalaf adalah:
1. Syarat yang berkenaan dengan mukalaf, yaitu mukalaf dalam keadaan hidup, mukalaf adalah manusia, dan bukan hewan ataupun tumbuhan, mukalaf harus sudah baligh, berakal, memahami perintah dan larangan, memiliki kemampuan untuk memilih, memiliki kecakapan untuk melaksanakan, dan beragama Islam.
2. Syarat yang berkenaan dengan beban perintah dan larangan yang ditujukan kepada mukalaf, yaitu objek perintah dan larangan harus belum terlaksana, objek perintah dan larangan harus merupakan hasil dari perbuatan mukalaf sendiri, objek perintah dan larangan harus diketahui oleh mukalaf, objek perintah dan larangan harus sesuai dengan syariat, dan objek perintah dan larangan haruslah sesuai dengan kemampuan mukalaf.
Sedangkan kedudukan hukum taysîr dalam hukum taklif terbagi dua, yaitu: pertama, kedudukan hukum taysîr pada objek perintah dan larangan yang dapat dipikul oleh mukalaf, baik dalam ibadah maupun mumalat. Imâm al-Syâthibî menjelaskan bahwa pada hakikatnya, objek perintah dan larangan pasti mengandung unsur kesukaran, namun kesukaran semacam ini adalah kesukaran lazim yang dapat dibebankan. Inilah yang dimaksud dengan kesukaran (al-masyaqqah) sesungguhnya. Ibn ‘Abd al-Salâm memberikan contoh seperti hakikat air dingin yang digunakan saat wudhu atau mandi adalah kesukaran yang lazim dan umumnya dapat dikerjakan oleh mukalaf. Dalam hal ini, Allah Swt. telah memberikan hakikat taysîr ke dalam objek perintah dan larangan, sehingga hukum taklif tersebut tidak dapat dikurangi atau dihilangkan dari pembebanan kepada mukalaf dengan alasan kesukaran.
Kedua, kedudukan hukum taysîr pada objek perintah dan larangan yang tidak dapat dipikul oleh mukalaf, yaitu objek pekerjaan yang memiliki kesukaran berlebih dan sangat mustahil untuk dikerjakan oleh mukalaf. Para ulama ushul fikih memberikan contoh bahwa mustahil bagi mukalaf untuk mengerjakan dua perintah yang bertentangan di satu waktu tertentu. Atau objek pekerjaan yang memiliki kesukaran berlebih akan tetapi mukalaf dapat mengerjakannya dengan sekuat tenaga dan mempertaruhkan jiwa, seperti perintah puasa bagi mukalaf yang sakit keras. Dalam hal ini, Allah Swt. memberikan rahmat-Nya dengan meringankan perintah tersebut ke dalam hukum taysîr, dalam hal ini adalah rukhsah.
Taysîr dan Sistem Ekonomi Islam
Sejatinya, hukum Islam yang telah ditetapkan oleh Allah Swt., baik itu yang berkenaan dengan ibadah maupun muamalat, sudah sangat sempurna dan menyeluruh, sehingga permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh mukalaf dapat dikaji langsung dari Alquran dan Sunah Rasul-Nya. Hal ini sesuai dengan firmanNya, yaitu “Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu, cukupkan nikmat-Ku kepadamu, dan telah Aku ridhai Islam itu menjadi agama bagimu”. Berkaitan dengan taysîr, pada hakikatnya Allah Swt. telah melandasi hukum yang ditetapkan dengan unsur taysîr, baik dalam hukum asli (al-‘azîmah) ataupun hukum lanjutan (al-rukhshah).
Hal ini dikarenakan Allah Swt. mengetahui bahwa manusia sebagai mukalaf (terutama umat Nabi Muhammad Saw.) sangat membutuhkan sesuatu yang mudah dan meringankan dalam melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-Nya. Syariat yang ditetapkan oleh Allah Swt. kepada umat terdahulu berbeda dengan umat Nabi Muhammad Saw., misalnya dahulu sholat dilaksanakan 50 kali dalam satu hari, sedangkan umat Nabi Muhammad Saw. hanya melaksanakan 5 kali sholat fardu dalam satu hari. Muhammad Sa’ad al-Yûbî, menguraikan bahwa kesejatian Allah Swt. menjadikan syariat Nabi Muhammad Saw. mudah dan ringan adalah dalam rangka memberikan kemaslahatan dalam ibadah dan muamalat.
Dengan kata lain, kesejatian itu terletak di mukalaf yang membutuhkan kemudahan dan keringan. Secara logika, bagaimana mungkin Allah Swt. yang memiliki sifat pengasih lagi penyayang mempersulit dan membebani hamba-Nya, serta menyeru untuk beribadah namun memberikan kesulitan yang menghalangi mereka untuk dapat melaksanakan perintah tersebut. Ibn ‘Abd al-Salâm menegaskan bahwa sesungguhnya segala yang dikerjakan mukalaf adalah dalam rangka untuk taat, patuh, dan mendekatkan diri kepada Allah Swt., sehingga dikatakan bagaimana mungkin Allah Swt. menyulitkan hamba-Nya untuk taat, patuh, dan dekat kepada-Nya. Dalam hal ini, diberlakukanlah kemudahan dan keringanan bagi hamba-hamba-Nya. Imâm al-Syâthibî juga menegaskan bahwa dalam penerapan syariat tidak ada hal yang memberatkan dan menyulitkan sehingga mukalaf terbebani.
Di dalam sistem ekonomi Islam, para ekonom Muslim dan ulama fikih sepakat menyatakan bahwa aturan, prinsip, hukum, dan etika bermuara pada syariat yang diberikan oleh Allah Swt. kepada Rasulullah Saw. dan umatnya dalam bentuk teks dan maknawi yang terkandung di dalam Alquran dan Sunah. Syariat yang Allah Swt. berikan kepada umat Nabi Muhammad Saw. adalah syariat yang lengkap, dimana tidak mengandung kesukaran yang berarti dan bahkan terkandung di dalamnya kemudahan (al-taysîr) yang memungkinkan seorang mukalaf dapat melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-Nya.
Dalam sistem ekonomi Islam, misalnya, ada pembahasan mengenai kewajiban bekerja bagi kaum Muslim untuk memenuhi kebutuhan hidup, mendukung kegiatan ibadah, dan memenuhi hak orang lain yang di bawah tanggungannya. Kewajiban ini adalah perintah Allah Swt., yaitu “Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan” dan “Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain”. Rasulullah Saw. juga bersabda bahwa “Tidak seorang Muslim pun yang menanam tanaman, lalu dimakan oleh seekor burung atau manusia dan hewan, kecuali merupakan bentuk sedekah baginya”.
Dalam perintah bekerja ini, Allah Swt. tidak membatasi pekerjaan apa yang harus dilakukan mukalaf, bahkan memberikan keleluasaan bekerja. Namun demikian, Allah Swt. memberikan catatan bagi mukalaf bahwa pekerjaan mukalaf harus halal dan materi yang didapatkan dari hasil bekerja itu juga harus halal dan baik. Dari sistem ekonomi Islam di atas, dapat dicermati bahwa perintah bekerja yang diwajibkan oleh Allah Swt. kepada kaum Muslim tidak mengandung kesukaran yang berlebih. Hal ini dapat dilihat manakala Allah Swt. memberikan keleluasaan bagi mukalaf untuk dapat bekerja di bidang apapun, sehingga mukalaf dapat menyesuaikan kemampuannya dengan perintah Allah Swt. Bagi yang mampu berniaga, maka diperkenankan untuk bekerja dalam hal perniagaan. Bagi yang mampu bekerja di instansi, maka diperkenankan untuk bekerja di dalamnya. Jika tidak mengandung kesukaran berlebih, maka ini adalah kemudahan yang memberikan kemaslahatan bagi manusia tersebut. Meskipun di dalam perintah bekerja Allah Swt. memberikan catatan agar mukalaf bekerja di sektor yang halal dan memakan materi yang didapat dari bekerja itu adalah halal dan baik. Namun demikian, hal ini bukanlah kesukaran berlebih yang dimaksud sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Imâm al-Syâthibî di atas.
Dalam jual beli misalnya, Allah Swt. dan Nabi Muhammad Saw. tidak membatasi kaum Muslim untuk bertransaksi dengan kaum non-Muslim dan materi yang ditransaksikan juga diberikan keleluasaan. Batasan yang diberikan hanya masalah kehalalannya. Dalam hadis disebutkan: Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya melarang orang memperjualbelikan arak, bangkai, babi, dan patung-patung. Maka seorang dari sahabat bertanya: “Ya Rasulullah, tahukah kamu bahwa lemak bangkai digunakan untuk mengecat kapal dan meminyaki kulit dan untuk lampu penerangan?”. Rasulullah Saw. menjawab: “Semua itu tetap haram...”. Dalam riwayat lain disebutkan,Rasulullah Saw. bersabda: “Dua orang yang berjual beli berhak khiyâr (saling tawar menawar) selama belum berpisah. Jika mereka berlaku jujur dan berterus terang, diberkahilah jual beli mereka. Tetapi jika tidak berterus terang dan berbohong, dihapuskanlah berkah jual beli mereka.” (H.r. al-Bukhârî).
Berdasarkan beberapa ayat Alquran dan Hadis, dapat dicermati bahwa Allah Swt. tidak membebani mukalaf dengan kesukaran yang berlebih. Bahkan Allah Swt. dan Rasul-Nya memberikan contoh kemudahan (al-taysîr) dan keleluasaan kepada kaum Muslim dalam bertransaksi dengan kaum non-Muslim. Sesuatu yang akan sangat menyulitkan jika kaum Muslim bertransaksi/jual-beli hanya kepada sesama kaum Muslim. Akan tetapi hal ini tidak diberlakukan oleh Allah Swt., mengingat jual-beli mengandung kemaslahatan bagi semua manusia.
Penerapan Taysîr dalam Sistem Ekonomi Islam
Ya’qûb al-Bahusayn menjelaskan bahwa salah satu dari faktor diperkenankannya kemudahan (al-taysîr) adalah adanya kesukaran (al’usr) dan keumuman permasalahan yang sering terjadi (‘umûm al-balwâ).
Dalam kegiatan ekonomi, terkadang ada kesukaran yang sering dihadapi oleh para pihak yang bertransaksi, seperti kesukaran untuk bertemu dan bertransaksi face to face. Padahal adanya pertemuan dalam bertransaksi merupakan sesuatu yang telah diisyaratkan oleh Rasulullah Saw. Maka dalam hal ini, banyak ulama fikih yang berpendapat bahwa untuk menghilangkan kesukaran tersebut diperkenankan para pihak menggunakan media telekomunikasi seperti telepon, sms, atau internet, sehingga syarat bertemu dan bertransaksi face to face yang tersirat dalam Hadis tersebut terpenuhi.
Adapun keumuman permasalahan yang sering terjadi (‘umûm al-balwâ) dan selalu ditemukan adalah seperti terbungkusnya komoditi yang diperjualbelikan sehingga menyulitkan seorang pembeli untuk mengetahui keadaan fisik komoditi tersebut. Dalam hal ini, para ulama fikih berpendapat bahwa untuk menghilangkan keumuman permasalahan yang sering terjadi dan selalu ditemukan adalah dengan membuka salah satu pembungkus komoditi tersebut untuk dijadikan contoh, sehingga seseorang yang akan membelinya dapat mengetahui kondisi fisik komoditi tersebut.
Penerapan konsep taysîr dalam sistem ekonomi Islam dihadirkan dalam rangka untuk memberi kemudahan, keringanan, dan kemaslahatan bagi para mukalaf. Baik di dalam hukum asli (al-‘azîmah) maupun hukum lanjutan (al-rukhshah) yang berkenaan dengan sistem ekonomi Islam. Taysîr dihadirkan oleh Allah Swt untuk memberi kemaslahatan dan kemudahan bagi manusia, sehingga tidak ada alasan bagi manusia untuk tidak menjalankan perintah dan menjauhi larangan-Nya, terutama yang berkenaan dengan kegiatan bisnis dan ekonomi.
Saat ini, dunia perbankan syariah dan industri syariah yang berkembang pesat, sangat membutuhkan perangkat hukum dalam rangka untuk menciptakan produk dan inovasi kreatif, sebagai konsekuensi tuntutan zaman dan kebutuhan manusia yang terus berkembang. Konsep hukum taysîr sangat dimungkinkan untuk menjawab kebutuhan di atas. Konsep ini sangat mencerminkan kemudahan dan kelenturan agama Islam, serta ketegasannya di dalam menjawab tantangan zaman.
Namun demikian, penerapan konsep ini tidak serta-merta dibenarkan tanpa memperhatikan maksud Allah Swt melegalkan hukum (maqashid al-syarî’ah), terutama dalam hal menjaga harta. Hal ini dilakukan untuk menjaga mukalaf tetap patuh dan taat dengan syariat yang telah ditentukan dan terhindar dari perbuatan yang meremehkan atau menggampangkan hukum (al-mutasâhilûn fî al-ahkâm).




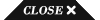

Post a Comment